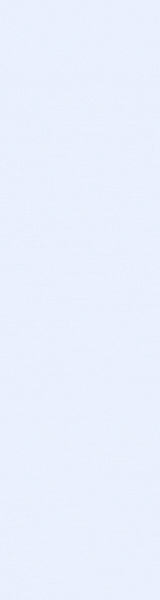PROFESI-UNM.COM – Saya pribadi memandang bahwa pendidikan di Nusantara sebelum datangnya kolonialisme bukan sekadar proses transfer pengetahuan, melainkan upaya memanusiakan manusia. Pendidikan tumbuh dari pemahaman hidup, relasi sosial, dan spiritualitas yang mendalam, bukan dari kebutuhan administratif atau kepentingan ekonomi.
Di Sulawesi Selatan, masyarakat Bugis telah lama hidup dengan nilai Sipakatau (saling memanusiakan), Sipakalebbi (saling menghargai), dan Sipakainge (saling mengingatkan). Nilai-nilai budayan ini bukan konseptual semata, melainkan pendangan hidup yang membentuk cara seseorang bersikap di tengah masyarakat.
Pada masa kolonialisme itu, seseorang dianggap “ada” secara sosial bukan karena gelar atau kepintarannya, akan tetapi karena kemampuannya menjaga martabat sesama. Pendidikan semacam inilah yang membentuk mental sosial masyarakat Nusantara jauh sebelum sistem pendidikan formal ala Barat diperkenalkan.
ADVERTISEMENT
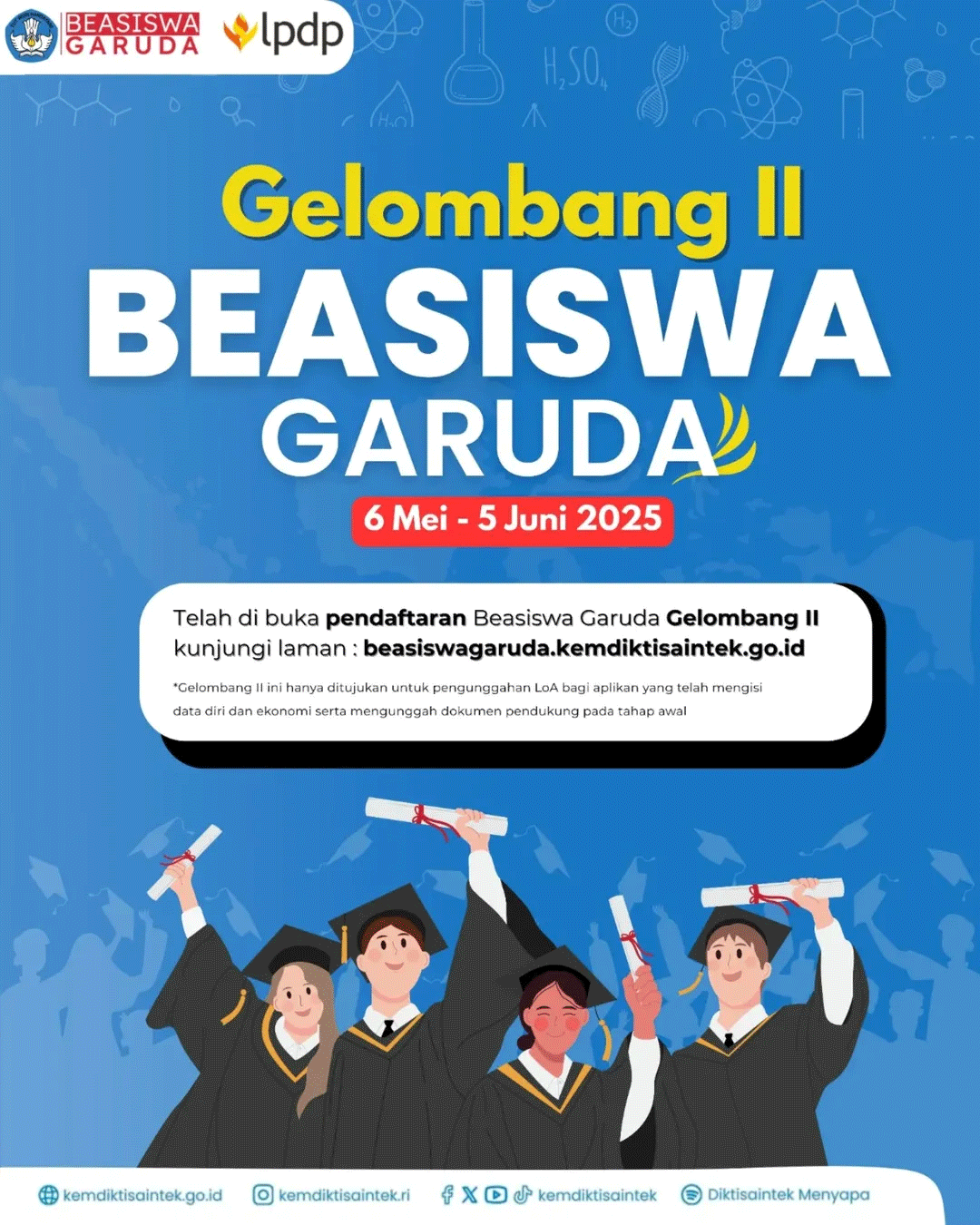
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kehidupan nyata dapat dilihat pada tata cara hidup masyarakat Ammatoa Kajang di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Bagi mereka, pendidikan pertama adalah pelajaran tentang kesederhanaan dan pendekatan masyarakat dengan alam yang diwariskan melalui Pasang Ri Kajang. Tanpa sekolah formal, anak-anak di suku Kajang diajarkan hidup setara disimbolkan melalui pakaian hitam serta diwajibkan menjaga hutan adat Borong Ta’rappang.
Saya pribadi menilai bahwa kesadaran mereka akan relasi manusia dan alam menunjukkan kecerdasan ekosistem yang kuat, bahkan sebelum konsep pendidikan lingkungan dikenal secara modern.
Dalam masyarakat Bugis-Makassar, pendidikan karakter juga diwariskan melalui sastra tutur dan pesan leluhur. Pappaseng menjadi sarana pembelajaran moral yang menanamkan nilai Siri’ sebagai penggerak sikap hidup.
Nilai ini berjalan seiring dengan lempu (kejujuran) dan geteng (keteguhan memegang janji), yang menjadi fondasi stabil antara sosial dan politik kerajaan-kerajaan Nusantara.
Relasi antara guru dan murid dalam sistem pendidikan tradisional bersifat personal dan sarat keteladanan. Seorang Puang atau guru dihormati bukan karena sertifikasi, melainkan karena kedalaman pemahaman terhadap adat dan kekuatan moralnya. Status sosial dibangun di atas kualitas budi pekerti, bukan dari berapa banyak materi yang dikuasai.
Prinsip Sipakalebbi menjaga agar tidak ada ruang bagi kesombongan, karena setiap manusia dipandang memiliki martabat yang layak dihormati. Masuknya kolonialisme membawa pergeseran besar dalam arah pendidikan. Sekolah-sekolah kolonial dirancang untuk mencetak tenaga administratif yang patuh, bukan manusia yang berakar pada budaya dan tanahnya. Nilai-nilai lokal seperti Sipakatau perlahan tergeser oleh logika kompetisi dan individualisme. Akibatnya, saat ini banyak individu menjadi cerdas secara intelektual, tetapi kehilangan keterikatan dengan identitas budayanya sendiri.
Penutup saya pribadi meyakini bahwa masa depan pendidikan Indonesia perlu kembali berpijak pada akar budayanya. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Bugis-Makassar dan suku Kajang bukan romantisme masa lalu, melainkan landasan penting untuk menjawab krisis moral hari ini. Pendidikan seharusnya kembali menjadi ruang pembentukan budi pekerti dan kesadaran sosial, bukan sekadar pencetak manusia cerdas secara teknis. Tanpa landasan nilai seperti Sipakatau dan kesahajaan ala Ammatoa, pendidikan berisiko melahirkan generasi yang pintar, tetapi tercerabut dari jiwanya sendiri.
HIDUP MAHASISWA, HIDUP MAHASISWA, DAN HIDUP RAKYAT INDONESIA. (*)
*Penulis: Muhammad Adnan Ramadhan