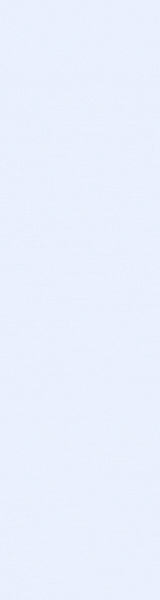PROFESI-UNM.COM – Menginginkan masyarakat yang maju dan berperadaban hanyalah angan-angan, tanpa dimulai dengan pendidikan yang membebaskan, bukan menindas. Pendidikan yang dialogis, bukan pendidikan yang feodal. Pendidikan yang murah dan mudah diakses, bukan pendidikan yang cenderung menjadi komoditas. Persoalan ini bukan hanya menyangkut aspek aksesibilitas dan kualitas, tapi berakar pada masalah politik pendidikan, struktural, dan kultural.
Rasa-rasanya pendidikan saat ini belum mampu membangun kesadaran kritis dan belum mampu mengembangkan potensi manusia (peserta didik) sesuai dengan keinginan dan kemapuannya seperti yang dicita-citakan Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan saat ini cenderung tidak menyenangkan dan sekolah berubah menjadi penjara-penjara kecil yang membatasi dan mengekang karena praktik feodalisme yang tercipta didalam kelas. Sekolah dan proses pendidikan menjadi alat produksi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menjadikan esensi pendidikan sebagai proses humanisasi tergerus oleh logika pasar.
Guru yang semestinya menjadi hidden curriculum berubah menjadi karyawan sekolah disibukkan dengan pelaporan kegiatan, pengisian sistem informasi, serta evaluasi administratif ketimbang proses pembelajaran yang bermakna. Fenomena semacam ini dikritisi oleh Henry Giroux yang memperkenalkan konsep teacher as a transformative intellectual. “Bahwa guru seharusnya menjadi agen perubahan sosial, bukan sekadar pelaksana kurikulum”. Guru menjadi kurikulum yang berjalan dapat memodifikasi proses pembelajaran yang menyenangkan, dialogis, dan partisipatif agar guru tidak kehilangan otonominya karena sistem pendidikan yang sangat birokratis.
ADVERTISEMENT
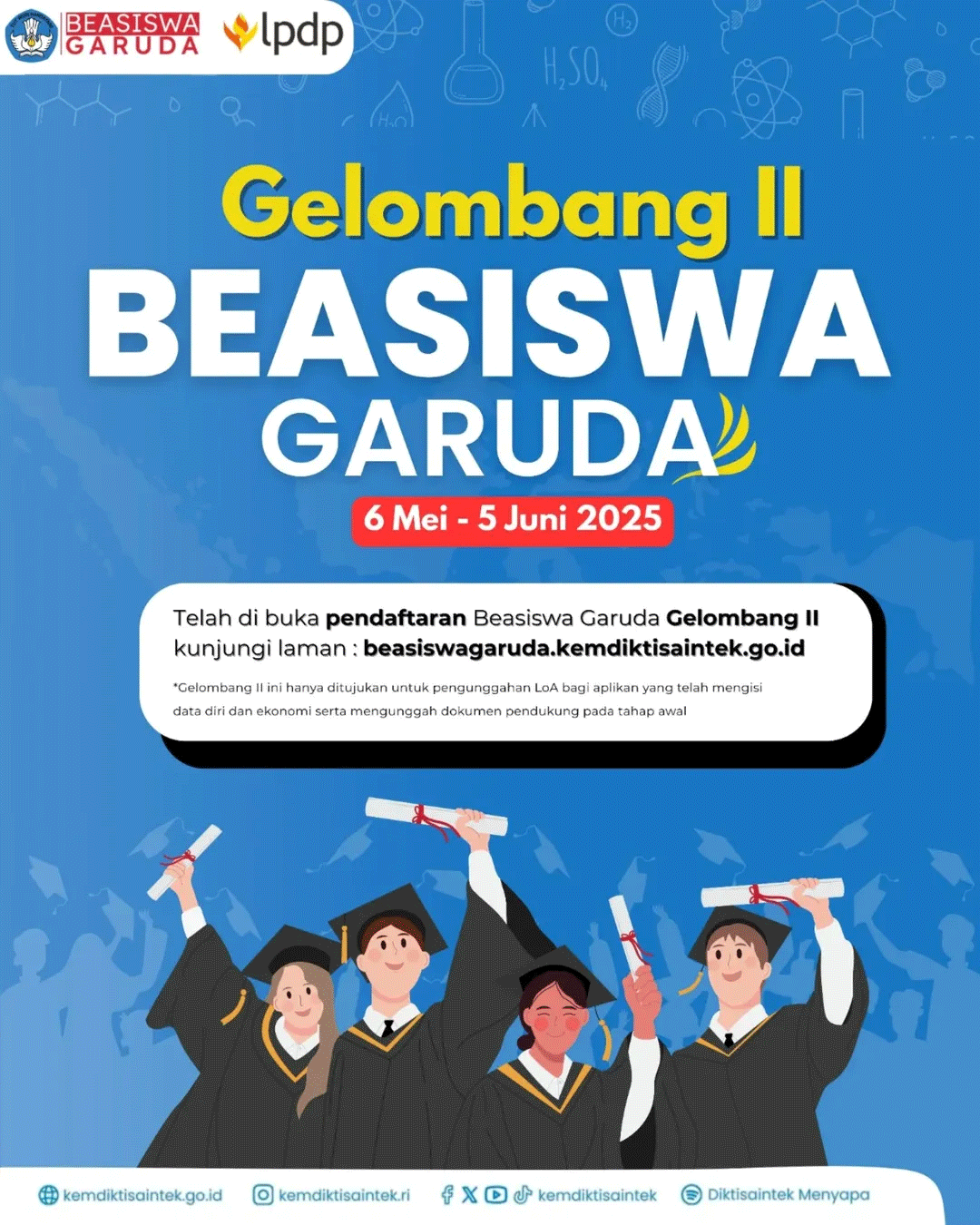
SCROLL TO RESUME CONTENT
Konflik kepentingan antar lembaga sering kali menjadi penghambat utama reformasi dibidang pendidikan. James C. Scott dalam Seeing Like a State (1998) mengatakan kebijakan negara mengenai pendidikan terlalu teknokratik dan tidak memperhitungkan konteks lokal sering kali gagal dan justru menimbulkan masalah baru. Misalnya, kurikulum berganti sesuai dengan selera menteri. Pendidikan di Indonesia pun tidak luput dari kecenderungan ini, banyak kebijakan didesain secara top-down tanpa melibatkan aktor-aktor pendidikan di akar rumput (bottom up).
Pendidikan sebagai proyek Emansipasi
Pendidikan dapat menjadi proyek emansipasi terutama dalam negara demokrasi, memang tidak ada bentuk pendidikan yang benar-benar ideal dalam perkembangannya. Setidaknya sistem pendidikan itu dianggap sebagai bentuk emansipasi dalam suatu negara, pendidikan yang membebaskan dan memberdayakan. Pendidikan mesti mampu membangkitkan kesadaran kritis, bertindak untuk mengubah ketidakadilan, dapat membantuk warga negara yang aktif dan berdaulat. Dari landasan pemikiran semacam ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan dari segi konsep, kebijakan dan praktiknya. Agar pendidikan tidak berubah bentuk menjadi proses yang kaku, feodal, dan sentralistis.
Jika pendidikan dianggap sekadar proses transfer pengetahuan, maka ini sama sekali tidak mencerminkan Trilogi pendidikan ala Ki Hajar Dewantara (Ing Ngarsoa sung Tulodho, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani), tetapi pendidikan juga menjadi proses pembentukan karakter dan sebagai perjuangan ideologis yang memengaruhi struktur sosial dan politik masyarakat. Kira-kira inilah yang dapat kita sebut sebagai proyek emansipasi. Bentuk pendidikan sebagai proyek emansipasi seperti upaya sadar untuk membebaskan individu dari belenggu ketidaktahuan, ketidakadilan, dan ketimpangan sosial. Emansipasi di konstruksi dalam pendidikan untuk membentuk manusia merdeka yang mampu berpikir kritis, mandiri, dan berpartisipasi aktif dalam transformasi sosial.
Konsep ini bertolakbelakang dengan pendekatan pendidikan tradisional yang feodalistis, teknokratis, dan reproduktif terhadap struktur dominasi. Sekolah dan pendidikan mereproduksi kapital budaya dan status sosial. Alih-alih menjadi alat mobilitas sosial, sekolah dan proses pendidikan seringkali memperkuat ketimpangan melalui mekanisme tersembunyi seperti pengkotak-kotakan sesuai dengan struktur sosial. Pendidikan sebagai proyek emansipasi menempatkan peserta didik sebagai subjek yang aktif, sadar, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosialnya. Melalui pendekatan dialogis, kritis, dan reflektif, pendidikan dapat menjadi kekuatan transformasi sosial yang membebaskan dari ketidakadilan struktural, ketidakadilan ekonomi dan dominasi ideologis.
Keadilan dan Kesetaraan dalam Pendidikan
Indonesia dengan bangga menyebut dirinya sebagai negara demokrasi mencita-citakan keadilan dan kesetaraan. Tentu salah satunya adalah keadilan dan kesetaraan dalam pendidikan negara demokrasi mesti menjamin akses yang adil bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, suku, agama, status ekonomi dan jenis kelamin. Pandangan ini sejalan dengan teori justice as fairness dari John Rawls (1971), yang menyatakan “bahwa institusi publik, termasuk pendidikan, harus diatur sedemikian rupa agar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kelompok yang paling kurang beruntung”.
Akses pendidikan mudah, murah dan sekolah tidak lagi mempraktikkan pengkotak-kotakan maka akan tercipta keadilan dan kesetaraan dalam praktik pendidikan. Sebaliknya, jika pendidikan mahal dan sulit diakses maka yang terjadi adalah ketimpangan struktural. Keadilan dan kesetaraan dua hal yang sukar ditemukan dalam institusi dan proses pendidikan. Padahal, Keadilan dan kesetaraan merupakan dua prinsip fundamental yang menjadi pilar bagi terwujudnya sistem pendidikan yang demokratis dan inklusif. Keadilan mengacu pada upaya memberikan setiap individu apa yang menjadi hak dan kebutuhannya, sementara kesetaraan memberikan akses yang sama kepada semua orang tanpa diskriminasi.
Dalam konteks ini, keadilan dan kesetaraan bertujuan untuk memastikan bahwa latar belakang sosial, ekonomi, gender, agama, maupun geografis setiap orang tidak menjadi penghalang untuk memperoleh pendidikan yang murah tetapi berkualitas. Sistem pendidikan di banyak negara tanpa terkecuali Indonesia masih memperlihatkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan sehingga menghambat peningkatan sumber daya manusia. Akses pendidikan yang berkualitas masih sangat tergantung pada lokasi geografis dan status sosial ekonomi. Misalnya, sekolah-sekolah di daerah terpencil kerap kekurangan guru, fasilitas, dan anggaran. Sementara sekolah elite di kota-kota besar mendapatkan sumber daya yang melimpah. Ketimpangan ini diperparah oleh kebijakan pendidikan yang cenderung bersifat teknokratis dan menekankan standarisasi, tanpa memperhatikan keragaman konteks sosial peserta didik.
Pierre Bourdieu melalui teorinya tentang cultural capital dan reproduction (1977) menyoroti bagaimana sekolah justru mereproduksi ketimpangan sosial dengan mengutamakan nilai-nilai dominan kelompok elite. Akibatnya, peserta didik dari kelompok marjinal teralienasi karena tidak memiliki modal sosial dan budaya yang sesuai dengan tuntutan sistem pendidikan yang hegemonik. Pendidikan yang seharusnya menjadi mobilitas vertikal (social climbing) justru memperkokoh stratifikasi sosial yang ada. Pendidikan yang adil bukan berarti semua orang diperlakukan sama, tetapi setiap orang diberi perlakuan berbeda sesuai kebutuhan untuk mencapai kesetaraan. Hal ini tidak hanya menjadikan pendidikan sebagai alat mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi kekuatan emansipatoris yang menjembatani kesenjangan dan menciptakan tatanan sosial yang lebih adil dan setara.
Sekolah mesti menjadi ruang partisipatif bukan ruang Penjara
Sekolah idealnya menjadi ruang partisipatif yang mendorong kebebasan berpikir, dialog, dan kolaborasi.Tapi banyak sekolah justru menyerupai ruang penjara dalam arti simbolik penuh dengan kontrol, disiplin kaku, dan minim ruang ekspresi. Michel Foucault memberikan gambaran yang cukup komprehensif bahwa institusi seperti sekolah kerap mengadopsi “desain panoptikon” sebuah desain institusi dengan sistem penjagaan dan pengawasan yang ketat, konsep ini membuat semua peserta didik disekolah semacam dalam penjara. Dalam kondisi yang tertekan membuat peserta didik tidak berani untuk mengeksplor dan mengembangkan kemampuan mereka.
Pendekatan yang terlalu menekankan kepatuhan pada aturan formal yang kaku, kurikulum yang ditentukan dari atas, dan evaluasi berbasis angka menciptakan suasana otoriter yang menghambat tumbuhnya partisipasi peserta didik. Dalam sistem semacam ini, peserta didik diposisikan sebagai objek didik, bukan sebagai subjek dalam pembelajaran. Peserta didik tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, tidak diberi ruang untuk menyampaikan suara kritis, dan seringkali harus menyesuaikan diri dengan norma-norma yang tidak mereka pahami apalagi sepakati. Hal ini menjadikan sekolah gagal sebagai tempat untuk membentuk watak peserta didik yang demokratis, dan justru melatih mereka menjadi pasif dan teralienasi dari realitas sosialnya. (*)
*Penulis: Randiawan, M.Pd, Dosen Prodi PPKn, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar