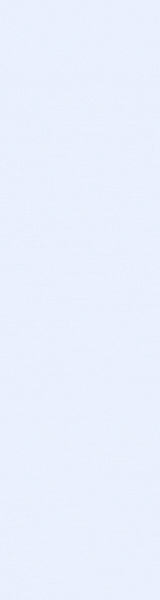PROFESI-UNM.COM – Saya menulis ini bukan sebagai aktivis yang hendak bernostalgia, juga bukan sebagai mahasiswa yang sedang kecewa karena kalah pemilihan ketua himpunan. Tulisan ini lebih menyerupai cermin yang sengaja saya hadapkan ke wajah sendiri. Saya pernah, dan masih duduk di bangku rapat lembaga kemahasiswaan, pernah merancang program kerja yang terdengar megah, serta pernah pula menjadi bagian dari panitia yang sibuk sampai lupa untuk benar-benar bertanya, “Semua ini sebenarnya untuk apa?”
Karena itu, kritik dalam tulisan ini pertama-tama tidak saya arahkan ke orang lain. Kritik ini justru saya tujukan kepada diri saya sendiri. Kepada versi diri saya yang dulu begitu bersemangat menyusun proposal, tetapi sering lalai membaca kebutuhan nyata mahasiswa. Kepada versi diri saya yang bangga melihat spanduk kegiatan terbentang lebar, namun jarang bertanya apakah setelah acara selesai ada perubahan yang sungguh terasa.
Keterputusan Realitas
Di atas kertas, lembaga kemahasiswaan digambarkan sebagai ruang belajar kepemimpinan dan tempat mahasiswa berlatih mengelola konflik, menyusun gagasan, serta bernegosiasi dengan realitas. Lembaga ini sering disebut sebagai laboratorium sosial yang mempersiapkan mahasiswa menjadi warga negara yang matang. Gambaran tersebut terdengar sangat ideal, bahkan nyaris heroik. Namun seperti banyak konsep indah lainnya, kenyataan tidak selalu berjalan seindah yang dibayangkan.
ADVERTISEMENT
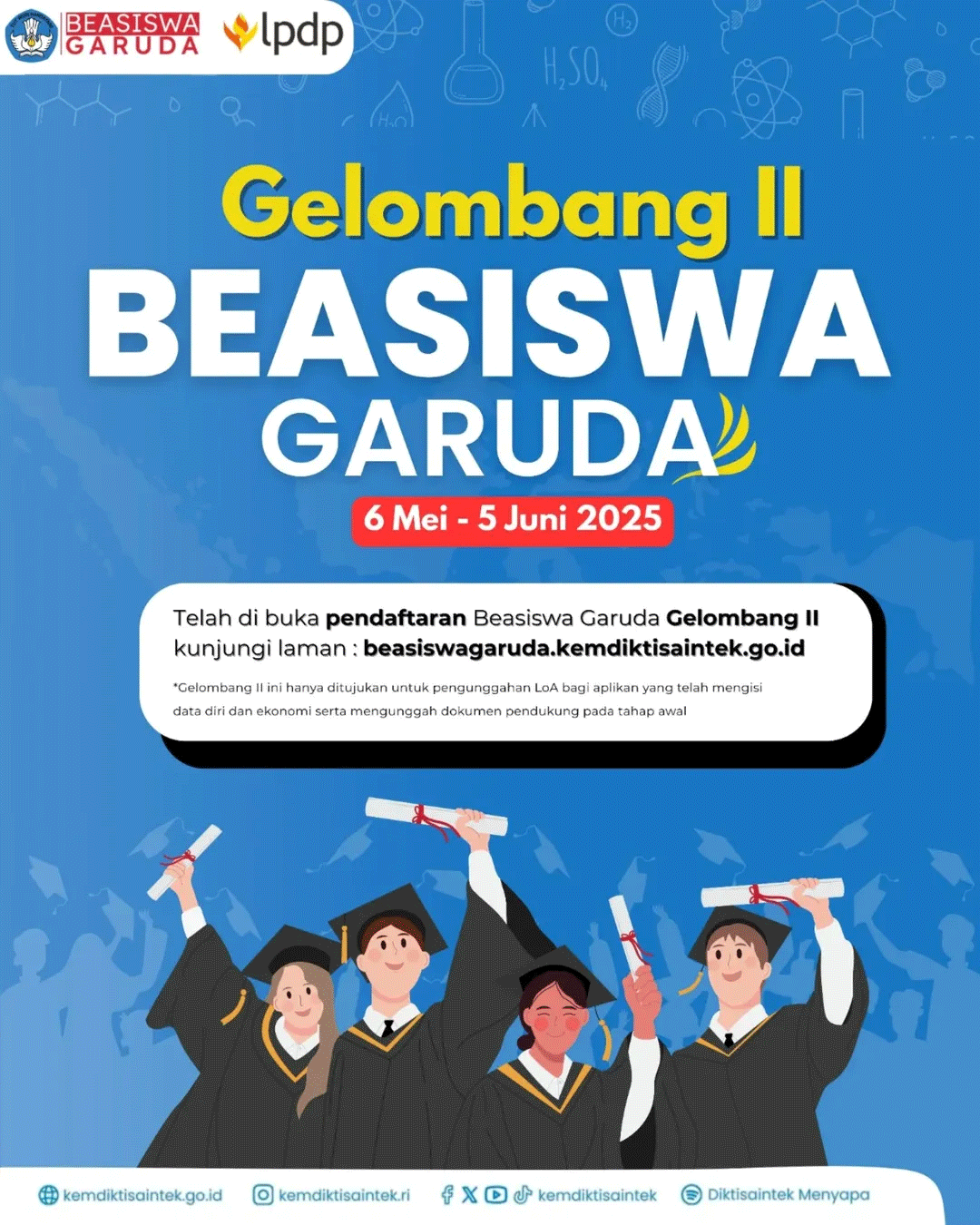
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perhatikan keseharian kampus. Banyak mahasiswa mengenal lembaga kemahasiswaan hanya dari baliho kegiatan atau jaket almamater yang dipakai beberapa orang di kantin. Nama badan eksekutif, atau himpunan jurusan mungkin terdengar familiar, tetapi fungsi dan perannya tidak benar-benar dipahami. Lebih jauh lagi, tidak sedikit mahasiswa yang merasa lembaga-lembaga tersebut jauh dari kehidupan akademik dan persoalan riil yang mereka hadapi. Seolah lembaga hidup di satu dunia, sementara mahasiswa mayoritas berada di dunia lain yang tidak pernah benar-benar terhubung.
Fenomena ini bukan semata kesalahan pengurus. Ada faktor struktural yang membuat lembaga kemahasiswaan perlahan berubah menjadi formalitas. Banyak program kerja disusun hanya demi memenuhi laporan pertanggungjawaban. Bahkan pemilihan ketua kadang lebih meriah dibandingkan realisasi janji setelah terpilih. Demokrasi kampus akhirnya berubah menjadi pesta musiman.
Di sisi lain, menutup mata terhadap peran historis lembaga kemahasiswaan juga tidak adil. Banyak tokoh nasional, pemimpin daerah, dan intelektual publik pernah ditempa dalam ruang-ruang organisasi kampus. Di sanalah mereka belajar berbicara di depan umum, menyusun argumen, berdebat secara terbuka, serta menerima kritik. Ruang organisasi menjadi semacam sekolah kedua yang tidak tercantum dalam kurikulum resmi namun diam-diam membentuk karakter dan keberanian berpikir.
Pergeseran Orientasi
Masalahnya sering kali bukan terletak pada keberadaan lembaganya, melainkan pada cara memaknainya. Ketika lembaga kemahasiswaan dipandang sekadar sebagai batu loncatan politik, orientasi kegiatannya akan condong pada pencitraan. Ketika jabatan organisasi dianggap sebagai tiket menuju popularitas atau karier, maka dampak jangka panjang tidak lagi menjadi prioritas.
Lalu muncul pertanyaan lanjutan, apakah solusi dari semua ini adalah membubarkan lembaga kemahasiswaan? Jawaban tersebut terasa terlalu sederhana. Menghapus lembaga tidak otomatis menghapus persoalan. Tanpa lembaga formal pun, kebutuhan mahasiswa untuk berkumpul maupun bergerak bersama akan tetap muncul dalam bentuk lain. Manusia pada dasarnya selalu mencari ruang kolektif untuk menyalurkan kegelisahan.
Hal yang perlu dipikirkan bukan soal ada atau tidaknya lembaga, melainkan bagaimana lembaga tersebut tetap hidup dan relevan. Relevansi tidak lahir dari struktur organisasi yang rapi atau aturan main yang tebal. Relevansi tumbuh dari kemampuan membaca zaman dan kebutuhan mahasiswa. Jika lembaga kemahasiswaan masih bekerja dengan pola yang sama seperti dua dekade lalu tanpa penyesuaian, wajar bila banyak mahasiswa merasa tidak terhubung.
Kegiatan seremonial yang diulang setiap tahun tanpa inovasi hanya akan melahirkan kelelahan kolektif. Mahasiswa hadir karena kewajiban atau ajakan teman, bukan karena merasa membutuhkan ruang tersebut.
Arah Pembenahan
Padahal potensi lembaga kemahasiswaan sangat besar. Ruang ini bisa menjadi jembatan antara teori di kelas dan praktik di lapangan, antara idealisme dan realitas. Lembaga tersebut dapat menjadi ruang advokasi bagi mahasiswa yang menghadapi masalah akademik, ruang diskusi untuk isu sosial, bahkan ruang eksperimen gagasan yang tidak selalu mendapat tempat di ruang kuliah formal.
Peran kampus juga tidak bisa diabaikan. Banyak lembaga kemahasiswaan bergerak dalam ruang yang serba terbatas. Dana yang minim, birokrasi berlapis, dan regulasi yang kaku acap kali menghambat kreativitas. Di sisi lain, kampus kerap menuntut lembaga menjadi representasi mahasiswa tanpa dukungan memadai.
Ironisnya, ketika lembaga kemahasiswaan tidak berjalan optimal, yang sering disalahkan hanya pengurusnya. Padahal persoalannya jauh lebih luas. Persoalan tersebut berkaitan dengan ekosistem kampus, budaya akademik, dan cara memandang peran mahasiswa.
Pertanyaan tentang relevansi sebenarnya bukan vonis akhir. Pertanyaan tersebut lebih menyerupai alarm. Alarm yang menandakan bahwa ada sesuatu yang perlu dibenahi. Lembaga kemahasiswaan tidak otomatis relevan hanya karena keberadaannya diakui. Relevansi harus terus diperbarui maupun dipertanyakan.
Barangkali langkah paling dasar adalah kembali pada pertanyaan awal, untuk siapa lembaga ini dibentuk? Jika jawabannya benar-benar mahasiswa, maka setiap program seharusnya berangkat dari kebutuhan mereka. Bukan dari tradisi lama, bukan dari ambisi personal, dan bukan dari keinginan untuk sekadar terlihat aktif. (*)
*Penulis: Muhammad Hilmi Assidiqy Yusuf