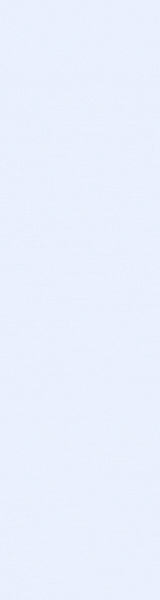PROFESI-UNM.COM – Menarik menyimak kembali pernyataan wakil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek-Dikti pada pemaparan visi-misi calon rektor yang lalu (Senin 26 Februari 2024), bahwa karakter kepemimpinan yang perlu direaktualisasi pada institusi pendidikan tinggi adalah academic leader, yang menurut Haedar Akib, atribut itu dulu disebut instructional leader dan sekarang disebut knowledge leader (Profesi edisi 190 Mei tahun XXXVIII 2015). Penulis sepaham dengan pemikiran para pakar yang menyatakan bahwa knowledge leader adalah individu yang terpilih secara sukarela melalui proses pemilihan elegan untuk menduduki jabatan sebagai pemimpin dalam organisasi berbasis pengetahuan, termasuk dalam institusi pendidikan tinggi seperti Universtas Negeri Makassar (UNM).
Dipahami bahwa pada setiap institusi pendidikan tinggi, pemimpinnya, Rektor bersama jajarannya dihadapkan pada situasi dan kondisi mengenai cara mengembangkan ilmu-amaliah dan amal-ilmiah dalam konteks pendidikan dan pengajaran (pembelajaran), penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, pengabdian kepada masyarakat, sebagai reaktualisasi dan revitalisasi Tri-Dharma Perguruan Tinggi. Realisasi tugas, fungsi dan peran academic leader mengacu pada filosofi bahwa institusi tempatnya bekerja memiliki beragam potensi dan kompetensi, solusi kreatif, dan kapabilitas untuk bersaing dan berubah. Oleh karena itu, motivasi dasar bagi sebagian orang yang bekerja dalam organisasi, seperti gaji, kedudukan, atau titel tidak lagi menjadi prioritas utama bagi academic leader. Pertanyaan retorisnya adalah mengapa academic leader diperlukan dalam organisasi berbasis pengetahuan seperti di UNM, seperti apa potret academic leader sebagaimana diharapkan oleh pihak Kementerian waktu itu, dan bagaimana dampak gaya kepemimpinan kreatif-inovatif academic leader terhadap keunggulan daya saing institusi yang dipimpin.
Jawaban pertanyaan retoris tersebut didasarkan pada pemikiran Haedar Akib berjudul Potret Diri Selaku Academic Leader (Profesi edisi 190 Mei Tahun XXXVIII 2015). Menurutnya, academic leader pada organisasi berbasis pengetahuan adalah bahwa dalam “jantung” perubahan organisasi senantiasa melibatkan pemimpin, atau seperti ungkapan “leader create culture” berbudaya sipakatau, sipakainge, sipakalebbi dalam khazanah budaya lokal Bugis-Makassar, bukan Sipakalarro atau saling menjatuhkan. Signifikansi peran academic leader didasarkan atas asumsi bahwa pengetahuan (tacit, explisit, cultural, etc.) dapat lebih bermakna karena diekspresikan penggunaannya oleh orang-orang yang berkompeten yaitu academic leader atau knowledge leader, yang di perguruan tinggi diperankan oleh akademisi dengan tugas tambahan selaku Rektor bersama jajarannya.
ADVERTISEMENT
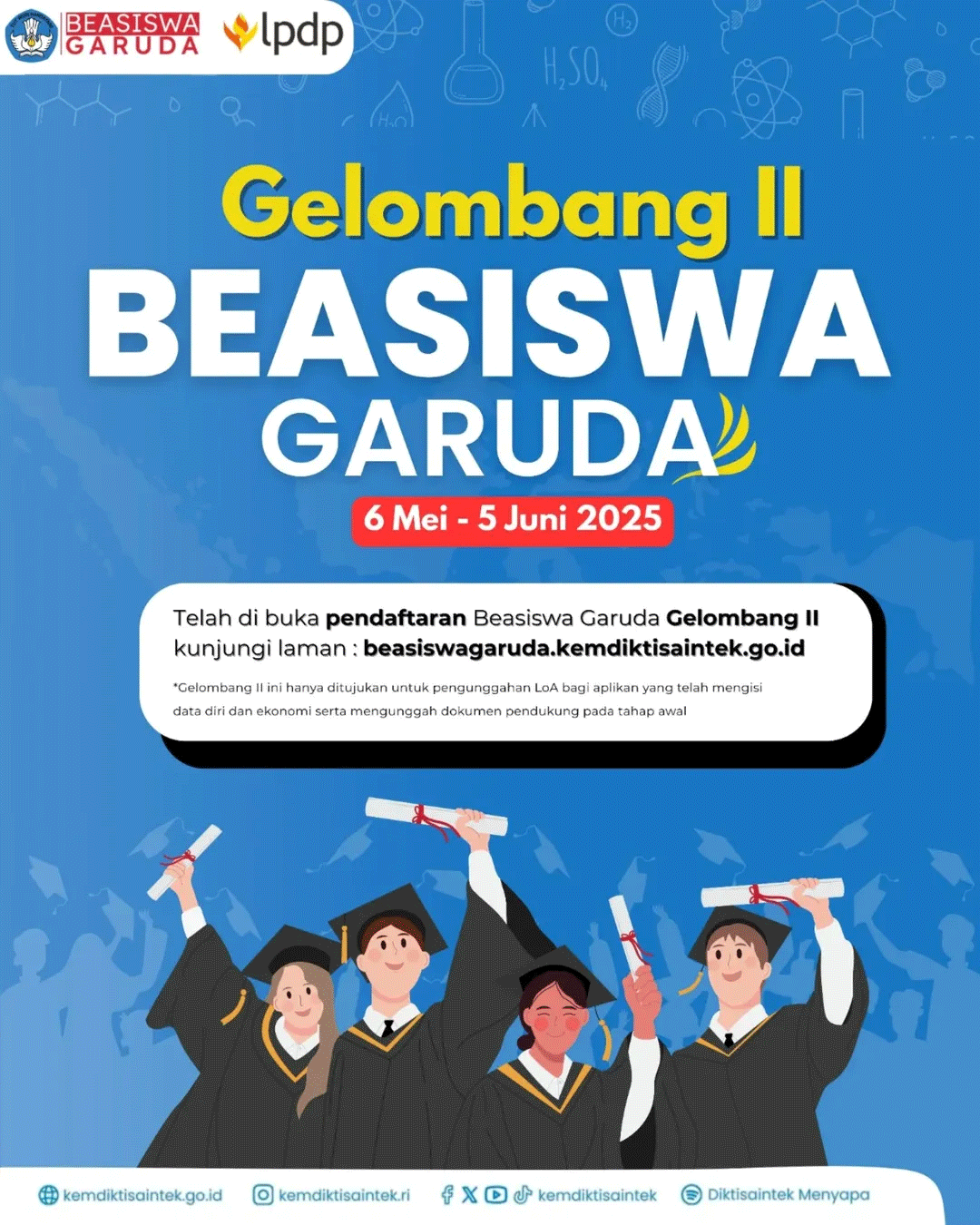
SCROLL TO RESUME CONTENT
Potret diri academic leader tercermin melalui kinerja personal yang ditunjukkan, sebagaimana potret diri Bapak Prof. Dr. Ir. Husain Syam, M.TP., IPU, ASEAN Eng dalam memimpin UNM selama ini. Menurut sebagian orang bahwa standarisasi tugas yang ditetapkan bagi knowledge leader adalah kapabel dalam berkolaborasi dan mengembangkan strategi, metode, arsitektur dan proses manajemen pengetahuan; mengembangkan metode dan proses manajemen pengetahuan berupa pola Knowledge Management in Higher Education; berkolaborasi dengan kelompok jabatan struktural (Wakil Rektor, Direktur Program Pascasarjana, Dekan, Jurusan, Program Studi, dll.) dan fungsional (pustakawan, akuntan, administrator, teknisi, laboran, dll.) dalam memfasilitasi dan merevitalisasi inisiatif manajemen pengetahuan; mengidentifikasi dan mengubah tantangan menjadi peluang dan uang sebagai upaya perbaikan manajemen pengetahuan, sebagaimana motto UNM “Tetap Jaya Dalam Tantangan”; meningkatkan upaya berbagi pengetahuan melalui berbagai pertemuan ilmiah skala lokal, nasional dan internasional; memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara optimal, seperti SYAM-OK (System and Application Manajemen Open Knowledge) di UNM; mengembangkan strategi, praktik, dan inisiatif manajemen pengetahuan yang efektif dalam tata pamong institusi secara berjenjang; mengajukan kriteria yang memungkinkan institusi mengukur tingkat kemampuan dan kinerjanya dalam menyelaraskan (“harmonisasi”) modal intelektual yang dimiliki; mengembangkan kepekaan terhadap pemenuhan kebutuhan civitas akademika, pemangku kepentingan internal dan eksternal organisasi; serta belajar dari organisasi lain, khususnya institusi sejenis (kompetitor) dalam memberdayakan sumber daya pengetahuan yang dimiliki secara efisien, efektif dan berkelanjutan.
Pemahaman tersebut diperkuat oleh gagasan bahwa knowledge leader atau academic leader secara khusus mampu menyelaraskan dan menyatukan visi-misi, fungsi dan peran institusi yang beragam dalam konteks tri-dharma perguruan tinggi, sebagaimana UNM yang bervisi Kependidikan dan Kewirausahaan; memanfaatkan praktik terbaik atau desain strategi patok duga; mengembangkan budaya pembelajaran; berorientasi pada pelayanan yang memuaskan atau “membahagiakan” dan “mensejahterakan” warga kampus; memanajemeni kegiatan mengkreasi, membagi, menggunakan, dan menyimpan pengetahuan; melejitkan perilaku kreatif-inovatif orang-orang yang dipimpin karena mungkin ada yang terlupakan, sebagaimana saran Haedar Akib, (Mencermati Potensi Civitas Akademika yang Terlupakan, Profesi online 22 Maret 2024); mengembangkan kemitrausahaan dan kolaborasi dengan pemangku kepentignan; serta menjadi pejuang visioner untuk mensukseskan pembelajaran organisasi dan manajemen pengetahuan.
Dampak gaya kepemimpinan kreatif-inovatif academic leader terhadap keunggulan daya saing institusi yang dipimpin minimal terlihat dari nilai tambah yang disumbangkan di tempat kerja dan lingkungannya, misalnya UNM yang saat ini Berakreditasi Unggul. Pemahaman ini sesuai asumsi bahwa nilai tambah yang disumbangkan knowledge leader terlihat melalui upayanya mengarahkan strategi organisasi; memulai alur kegiatan secara kreatif, inovatif dan bermakna; memecahkan masalah secara cepat; mentransfer best practices; mengembangkan keahlian profesional; membantu organisasi memeroleh dan mengembangkan bakat orang-orang yang dipimpin; mengembangkan kreativitas dan inovasi organisasi, termasuk melakukan pembaruan ide, proses, struktur, sistem, layanan, produk serta kompetensi baru, dsb. Sebagaimana yang teraktualisasi dalam perubahan status UNM dari Satuan Kerja (SATKER) menjadi Badan Layanan Umum (BLU) yang Insyaa Allah menjadi Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH).
Mengacu pada keberagaman tanggung jawab moral academic leader tersebut, penulis sepaham bahwa minimal terdapat tiga aspek yang mendesak untuk direvitaslisasi yaitu membangun budaya kerja berbasis pengetahuan sebagai wujud ilmu-amaliah dan amal-ilmiah, menciptakan infrastruktur manajemen pengetahuan, dan menjadikan semua tugas-pekerjaan terlaksana secara efisien, efektif, dan berdampak berkelanjutan, selain peran pemimpin pengetahuan sebagai inovator, fasilitator dan akselerator pertumbuhan organisasi berbasis pengetahuan. Disamping peran-peran elementer yang telah ditunjukkan oleh instructional leader di UNM selama ini sesuai pandangan Smith dan Andrew (1990) dalam bukunya Instructional Leadership, yaitu sebagai resource provider, instructional resource, communicator, dan visible presence.
Eksistensi dan revitalisasi peran academic leader, instructional leader atau knowledge leader dalam melejitkan perilaku kreatif-inovatif orang yang dipimpin ini membawa dampak positif berkelanjutan terhadap penciptaan keunggulan daya saing individu dan organisasi berbasis pengetahuan di perguruan tinggi. Belajar dari pengalaman hasil penelitian yang dilakukan oleh Andersen Consulting Institute for Strategic Change bahwa nilai saham dari suatu institusi yang memiliki knowledge leader yang baik bertumbuh sebanyak 900 persen dalam kurun waktu sepuluh tahun, apabila dibandingkan dengan institusi yang kepemimpinannya buruk yaitu hanya mengalami pertumbuhan 74 persen dalam kurun waktu yang sama. Sedangkan Majalah Fortune dalam usahanya mengumpulkan organisasi yang disukai telah berhasil mengidentifikasi adanya persamaan dari organisasi yang baik. Dengan demikian, jelas bahwa tidak hanya ada satu determinan yang membuat organisasi menjadi lebih berkinerja, “tetapi ketika kita dipaksa untuk memilih salah satu faktor determinannya yang membuat perubahan besar, maka pilihannya adalah faktor kepemimpinan atau knowledge leader, atau Rektor. Menurut Warren Buffet, sebagaimana dikutip oleh Frances Hesselbein and Marshall Goldsmith (2005: 8) dalam bukunya berjudul On Mission and Leadership, bahwa “orang memilih pelukisnya, bukan lukisannya”, lebih daripada gagasan Goldsmith tersebut penulis sangat berharap kepada kita semoga Rektor sebagai reaktualisasi diri selaku academic leader ini merupakan refleksi pilihan tepat sebagai sokoguru kreasi pengetahuan dan lokomotif organisasi (Universitas Negeri Makassar) tempat kita bekerja. Semoga.
*Penulis: Civitas Akademika UNM