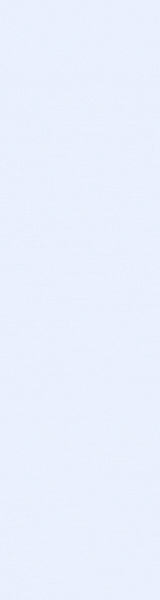PROFESI-UNM.COM – Dahulu, kita meyakini bahwa pendidikan adalah satu-satunya “eskalator” bagi anak-anak dari keluarga sederhana untuk memperbaiki nasib. Di ruang kelas, sekat-sekat antara si kaya dan si miskin diharapkan lebur. Namun, hari ini, eskalator itu seolah berhenti berfungsi bagi banyak orang. Alih-alih menjadi jembatan penyeberangan, pendidikan justru semakin nampak seperti benteng dengan tembok tinggi yang hanya memiliki celah pintu bagi mereka yang memiliki “kunci” finansial.
Fenomena mahalnya akses pendidikan bukan lagi rahasia umum. Mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, biaya menjadi variabel penentu yang sering kali lebih berkuasa daripada kecerdasan intelektual itu sendiri. Kita menyaksikan bagaimana istilah “Uang Pangkal” atau “Sumbangan Pengembangan Institusi” menjadi momok yang menakutkan bagi orang tua. Pendidikan yang berkualitas seolah-olah telah bermutasi menjadi barang mewah yang diberi label harga. Padahal, jika kita menengok Pasal 31 Ayat (1) UUD NRI 1945, mandatnya sangat lugas: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Hak ini bersifat universal, bukan hak eksklusif bagi mereka yang mampu menyetor sumbangan fantastis.
Realitas ini kian diperparah dengan melambungnya biaya di pendidikan tinggi. Kenaikan kelompok UKT (Uang Kuliah Tunggal) di berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memicu gelombang protes mahasiswa. Jalur mandiri, yang kuotanya semakin besar, sering kali menjadi “pasar gelap” akademik di mana bangku kuliah seolah dilelang kepada penawar tertinggi. Kondisi ini jelas-jelas menabrak Pasal 5 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menjamin bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.” Ketika mutu hanya bisa dibeli, maka kesamaan hak tersebut hanyalah tinggal slogan di atas kertas.
ADVERTISEMENT
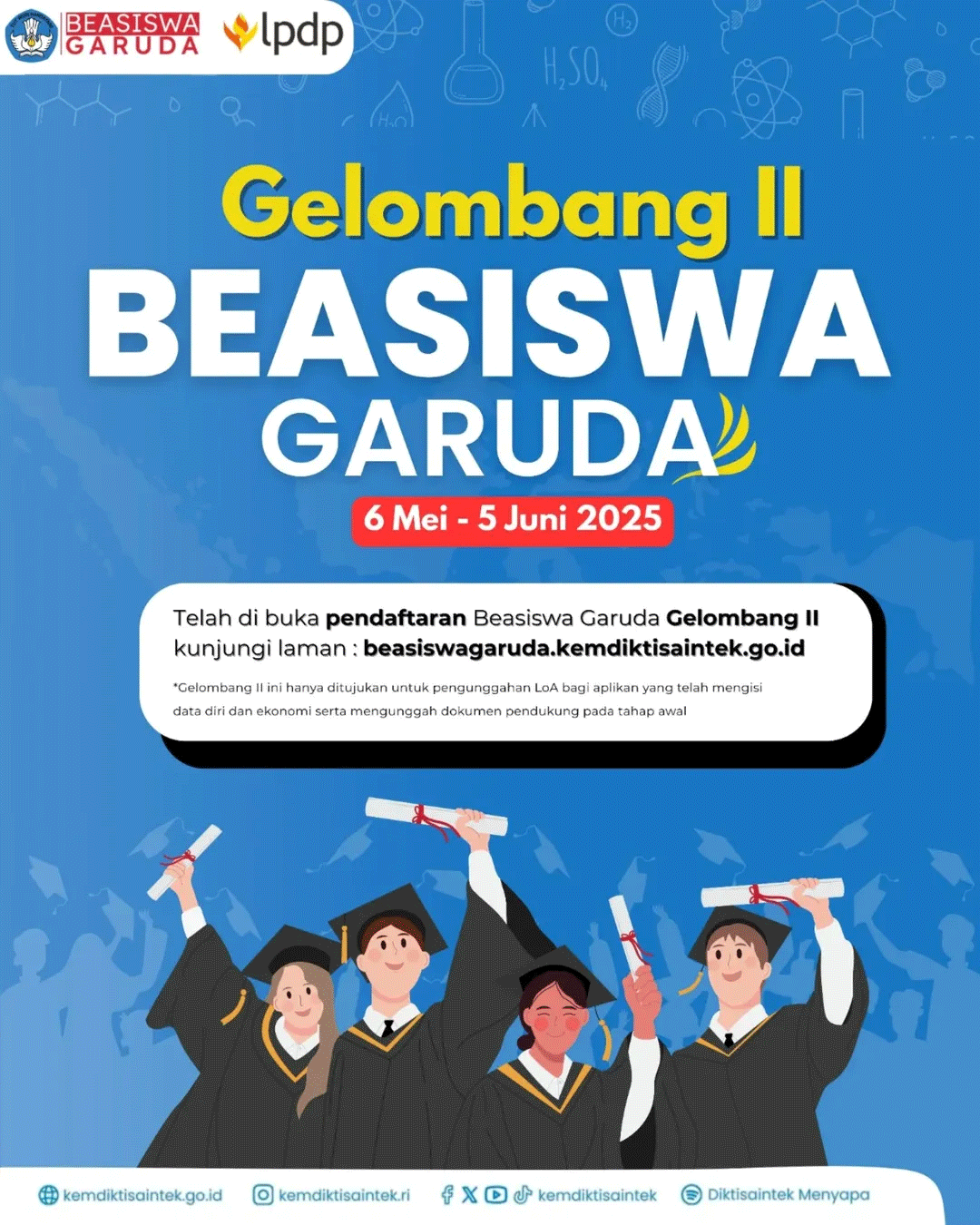
SCROLL TO RESUME CONTENT
Persoalannya bukan sekadar angka-angka di atas kertas tagihan. Masalah fundamentalnya adalah hilangnya roh inklusivitas. Inklusivitas harus berarti menyediakan kesempatan yang setara tanpa hambatan ekonomi, sesuai amanat Pasal 4 Ayat (1) UU Sisdiknas bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif.
Ketika bangku sekolah berkualitas lebih mudah didapatkan oleh mereka yang mampu membayar lebih, maka kita sedang melakukan seleksi sosial, bukan seleksi akademik. Kita sedang mengabaikan Pasal 76 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mewajibkan pemerintah dan perguruan tinggi memenuhi hak mahasiswa kurang mampu secara ekonomi agar dapat menyelesaikan studinya.
Dampak dari kondisi ini sangatlah fatal. Kita sedang menciptakan “kasta” baru dalam sistem sosial kita. Jika dibiarkan, pendidikan yang seharusnya memutus rantai kemiskinan justru akan menjadi alat untuk melanggengkan ketimpangan. Pemerintah memang telah meluncurkan berbagai program bantuan, namun sering kali hanya bersifat kosmetik yang tidak menyentuh akar masalah atau komersialisasi.
Kita seolah lupa pada Pasal 13 UU No. 11 Tahun 2005 (Ratifikasi Kovenan Internasional Hak EKOSOB) yang mencita-citakan pemberlakuan pendidikan Cuma-Cuma secara bertahap, bukan justru pendidikan yang semakin dikomersialkan. Sudah saatnya kita menagih kembali janji konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa syarat yang diskriminatif.
Negara harus hadir lebih kuat untuk memastikan bahwa biaya bukan lagi menjadi penghalang bagi anak bangsa untuk bermimpi. Meruntuhkan tembok tinggi di gerbang sekolah adalah sebuah keharusan. Jangan sampai di masa depan, kita mewariskan sebuah negara di mana hanya mereka yang berdompet tebal yang boleh memiliki cita-cita. Pendidikan harus dikembalikan pada fitrahnya, sebuah ruang publik yang inklusif, merakyat, dan menjadi milik semua kalangan. Sebab, kecerdasan tidak pernah memilih di rahim mana ia dilahirkan. (*)
*Penulis: Ardiansyah