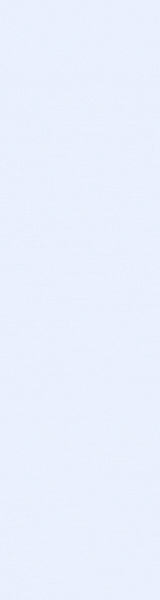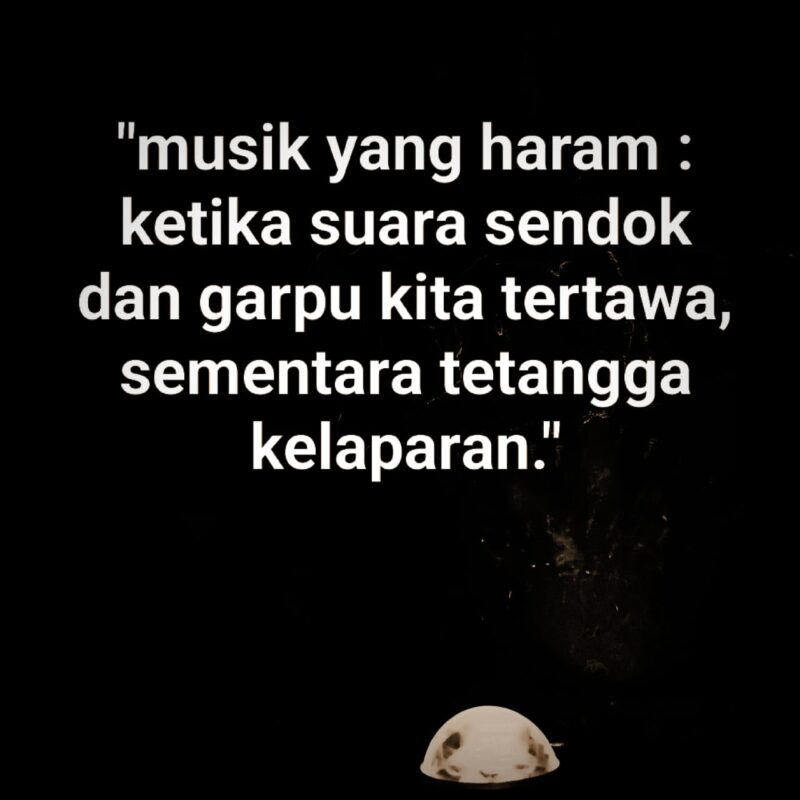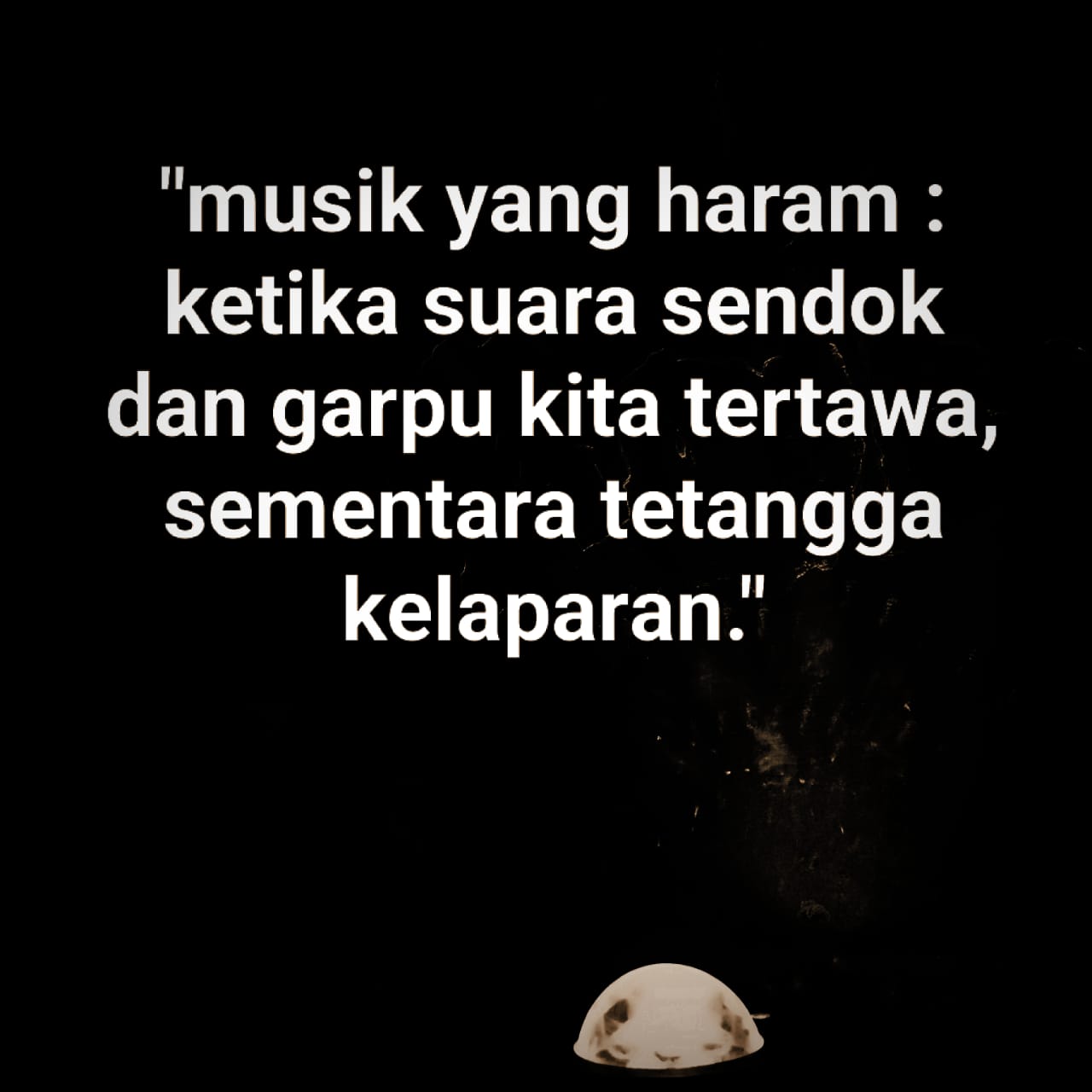
Di tengah kenyamanan hidup yang kita nikmati, seringkali kita lupa akan suara-suara yang sesungguhnya lebih layak didengar suara penderitaan dan ketidakadilan di sekitar kita. Pernyataan yang menggugah ini, “Musik yang haram adalah suara sendok dan garpu kita ketika makan, sedangkan tetangga kita kelaparan,” mengingatkan kita pada pentingnya kesadaran sosial dalam menikmati kehidupan. Sebuah gambaran yang jelas tentang ketidaksensitifan kita terhadap penderitaan orang lain, terutama ketika kita menikmati kelebihan, sementara mereka yang kurang beruntung tetap bergulat dengan kelaparan.
Dalam banyak budaya, makan bukan hanya sekedar aktivitas fisik untuk mengisi perut, tetapi juga merupakan simbol kebersamaan dan rasa syukur atas rezeki yang ada. Namun, di tengah kemewahan yang sering kali kita nikmati dengan piring penuh makanan lezat, meja yang dipenuhi hidangan, dan sendok garpu yang beradu ada kenyataan pahit yang jarang kita lihat. Di luar sana, ada tetangga kita, teman kita, atau bahkan orang asing yang tidak pernah tahu apa itu cukup makan, yang harus berjuang dengan perut kosong, mencari nafkah, atau bahkan bergantung pada bantuan untuk bertahan hidup.
Suara sendok dan garpu yang kita anggap biasa mungkin bahkan menghibur atau menenangkan dapat menjadi simbol ketidakpedulian kita. Sementara kita sibuk menikmati hidangan, kita acapkali lupa bahwa makanan adalah kebutuhan dasar yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Ketika kita terus berpesta dan memenuhi perut kita dengan beragam hidangan enak, di luar sana, ada yang terpaksa menghadapinya dengan perut keroncongan, bahkan tidak tahu apakah mereka akan mendapat makanan esok hari.
ADVERTISEMENT
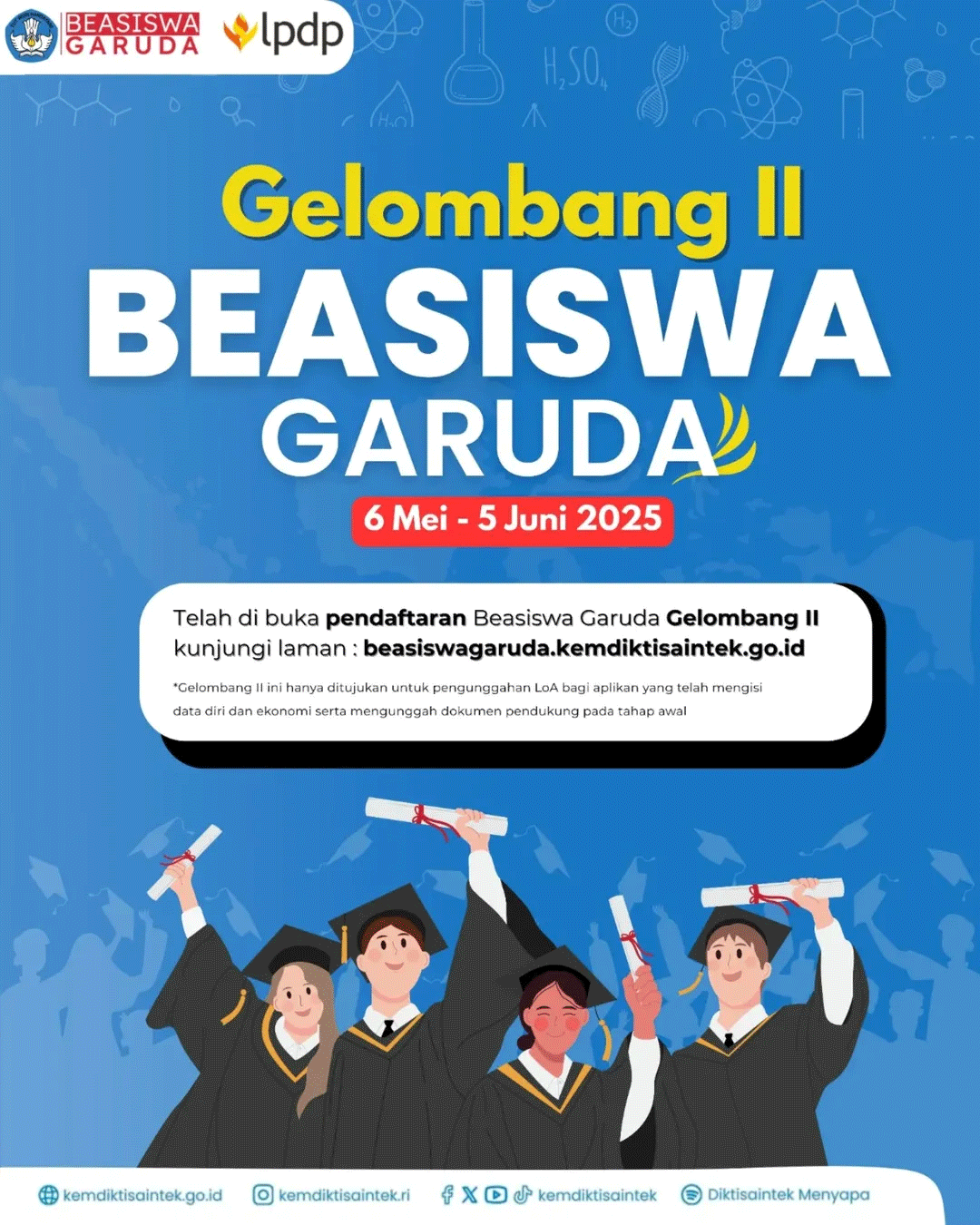
SCROLL TO RESUME CONTENT
Apa yang disebut sebagai “musik yang haram” dalam kalimat ini bukanlah soal moralitas atau agama semata, tetapi lebih kepada refleksi sosial. Ini mengajak kita untuk berpikir lebih dalam tentang prioritas kita sebagai individu, sebagai masyarakat, dan sebagai bagian dari dunia yang lebih luas. Seberapa sering kita membiarkan kenyamanan pribadi mengalahkan tanggung jawab sosial? Seberapa banyak dari kita yang meluangkan waktu untuk peduli pada mereka yang tidak seberuntung kita?
Pandemi global dan krisis ekonomi yang melanda beberapa tahun terakhir hanya memperburuk ketidaksetaraan ini. Meskipun di banyak tempat kita melihat tingkat konsumsi yang semakin tinggi, kita juga menyaksikan tingkat kemiskinan yang tak kunjung surut. Di tengah kemajuan ekonomi, ketimpangan yang terus melebar ini menjadi pengingat pahit bahwa kesenjangan sosial tak bisa dibiarkan terus membesar.
Pernyataan ini juga menggugah kita untuk merenungkan makna dari berbagi. Mungkin kita tidak bisa mengakhiri kelaparan dunia secara instan, tetapi kita bisa mulai dengan langkah kecil, seperti berbagi sedikit dari yang kita punya. Mungkin itu berupa uang untuk membeli makanan, menyumbangkan bahan makanan yang berlebih, atau sekadar membantu tetangga yang membutuhkan. Sebuah tindakan kecil yang bisa menjadi bagian dari solusi dalam mengurangi ketidakadilan sosial yang terjadi di sekitar kita.
Namun, perubahan tidak hanya datang dari tindakan individu. Masyarakat yang lebih peduli, yang lebih sadar akan ketimpangan sosial, adalah masyarakat yang lebih siap untuk mengubah struktur yang ada. Pemerintah, organisasi, dan lembaga sosial memiliki peran penting untuk menciptakan sistem yang lebih adil, yang menjamin bahwa setiap orang memiliki akses yang layak terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Tidak ada orang yang seharusnya dibiarkan kelaparan sementara sebagian lainnya hidup dalam kemewahan.
Akhirnya, musik yang sesungguhnya adalah suara dari kepedulian dan empati. Jika kita bisa mulai mendengarkan suara-suara di luar diri kita, mengerti penderitaan mereka yang kurang beruntung, dan bertindak untuk membantu mereka, maka kita akan benar-benar mendengar musik yang indah dan sejati, musik yang datang dari hati, bukan dari sendok dan garpu yang berdenting di meja makan kita. (*)
*Penulis adalah Ibnu Rasul Rahman, Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS) UNM