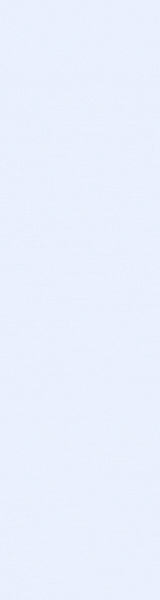PROFESI-UNM.COM – Siapa sangka ribuan followers di akun twitter, instagram, dan ribuan like di facebook, aku merasa menjadi ada. Hasil selfie kamera kualitas seadanya dan latar cahaya matahari senja atau warung kopi yang masih kurang kunjungan dengan dekorasi ala westernian maka aku merasa menjadi ada.
Aku merasakannya, walau akun twitter yang kuasuh sejak bertahun lalu kini tak bisa kugunakan lagi, instagram yang baru seusia jagung, dan facebook yang sepi dengan like karena kurangnya foto selfie full style. Maka aku sebagai pemuda merasa tidak ada.
Aku pemuda di masa edan. Semua serba tak terkejar lagi menurutku. Apalagi aku seorang pemuda desa yang pernah mengenyam pendidikan di kota besar. Sekembalinya aku ke desa membuatku menjadi tidak ada. Pemuda desa tidak sepopuler pemuda kota yang punya lifestyle dan gaya selfie yang cetar membahana. Maka saat ini aku berfikir, bahwa aku tidak ada.
ADVERTISEMENT
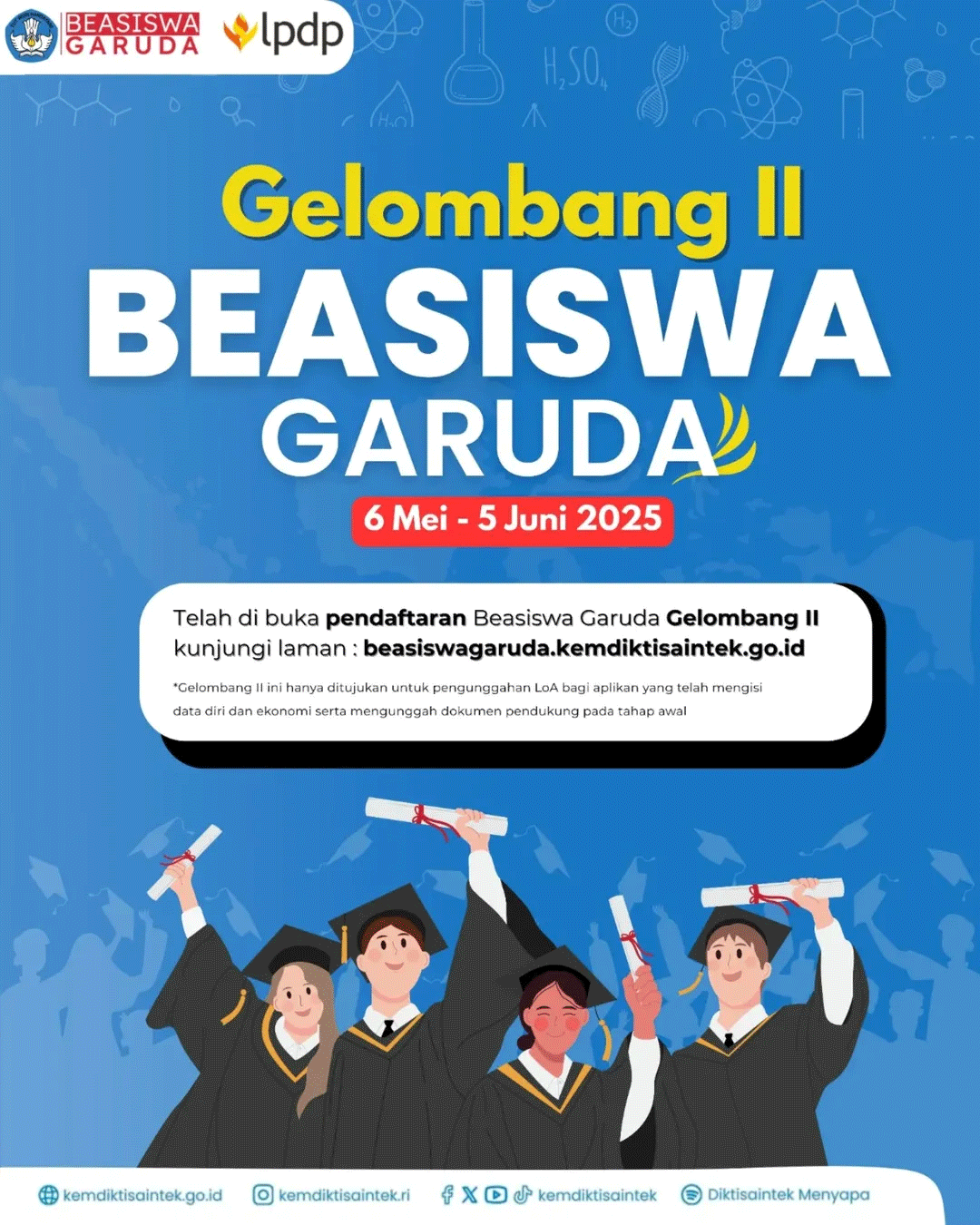
SCROLL TO RESUME CONTENT
Being (ada) bagi pemuda adalah penting. Tampil perfect di khalayak menjadi modal utama yang merupakan target dari pandangan orang lain. Jean Paul Sartre dalam buku Filsafat Eksistensialsme 2011, karya A. Setyo Wibowo menjelaskan “tatapan orang lain mengurangi kemungkinan-kemungkinan untuk menentukan dirinya sendiri dan mendorong manusia untuk mereduksi dirinya menjadi yang lain dan melepaskan kebebasan jati diri yang otentik”
Sejak media sosial menjadi alat bantu komunikasi utama bagi umat manusia, tatapan orang lain menjadi begitu pentingnya. Pemuda yang ada melakukan pemanfaatan ruang publik sebagai wadah kebebasan. Mengutip Setyo Wibowo dengan suatu refleksi sartrian manusia “ada untuk dirinya sendiri” lewat kesadaran transenden selalu bisa menidak, menghindar, dan menolak atas semua tatapan yang ada”
Pemuda benar-benar bebas atas apa yang dilakukan. Hal tersebut tidak pula membuat penulis menganggap mereka yang sibuk muncul di dunia maya dan mengabaikan dunianya yang ril tidak memiliki nilai apalagi nilai kepemudaan. Kebebasan atas being hanya digunakan untuk tampil sebagai objek tatapan tanpa “nilai”. Menggunakan perspektivisme Nietszche karya Roy Jakson “menggunakan hasrat adalah suatu bentuk kehendak untuk berkuasa”. Foto selfie hasil cepretan adalah bentuk aktualisasi diri yang penuh rasa simpati dan mempengaruhi orang lain untuk mencari tahu lebih dalam keadaan utuh yang terjadi rerhadap dirinya saat itu.
Melanjutkan hal tentang kontigensi (kebebasan) di ruang publik, saat ini aku merasa kalau kebebasan individu tersebut sangat rapuh dan cukup goyah. Era milenium saat ini tak ada ruang yang tidak diikat dengan aturan. Kita akrab benar dengan UU ITE yang telah banyak menjerat pemuda karena dianggap melakukan pelecehan terhadap terhadap orang lain. Inilah ruang publik yang rentan akan masalah-masalah yang bisa menghantam siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Pertarungan untuk merebut iba dari masyarakat digunakan orang banyak lewat media sosial.
Sibuk selfie sehingga ada hanya untuk dirinya menjadi paten dan pemuda mengabaikan kenyataan diluar darinya yang aku bisa katakan adalah society yang secara konkrit lebih butuh rasa simpati dan iba. Seberapa nyata tindakan kawan pemuda dalam melakukan pembelaan terhadap ketimpangan sosial yang terjadi pada ruang publik riil.
Buruh masih ditipu dengan penghisapan nilai lebih oleh kapitalisme monopoli, dengan skema yang saban hari semakin menggurita. Bermunuculan pula kasus human traficking yang terjadi di luar negara yang dampaknya senyata-nyatanya telah menelan korban buruh migran Indonesia. Cukup banyak kabar di media sosial membutuhkan dukungan gerakan dari pemuda untuk turut andil dalam mengkampanyekan keburukan sistem pemerintahan yang masih lemah memenuhi hak rakyat namun siap sepenuh hati memenuhi permintaan investor. Aku katakan, pemuda ada untuk dirinya sendiri walau di ruang publik sekalipun.
Bagi pemuda desa seperti saya, butuh pula perhatian yang jelas lebih kompleks dari kawan pemuda lainnya yang berpikiran maju, karena setiap tahun angka-angka yang dikampanyekan oleh media pilihan pemerintah menyatakan kalau ada keberhasilan dalam memajukan ekonomi di pedesaan. Tapi kenapa semakin hari aku semakin kesunyian lantaran banyak kawan pemuda berharap cemas pergi ke kota untuk berkerja dan memiliki cita-cita merubah nasib dan sekali-sekali bisa pula mengunggah foto selfie ngopi di starbucks mall kota.
Kebun kakao, sawah padi, dan kebun sayur sepi dari serbuan pict hunter. Tempat seperti ini menjadi absurd dan sulit dimaknai oleh pemuda masa kini. Lahan-lahan tersebut menjadi asing bagi mereka, dan aku menarik kesimpulan efek tidak massifnya selfie pemuda di lahan-lahan pertanian membuat lambat direalisasikannya reforma agraria sejati. Mungkin saja kan. Jadi mungkin saja kalau reforma agraria yang bakal direalisasikan adalah reforma agraria palsu.
Ratusan atau malah ribuan likers di sosial media tertentu menjadi indikator keter-ada-an seseorang pemuda saat ini. Eksis dan esensi tidak perlu lagi direnungi karena dunia saat ini cukup dinamis dengan masalahnya. Perlu dilakukan sekarang cukup being untuk diri sendiri, karena kesendirian seorang pemuda maka dia menjadi ada.
Namun kalau pemuda saat ini belum punya visi saat ingin keluar dari kesendiriaannya. Saya ingin memberikan saran seperti di bawah ini. Berikan aku sepuluh pemuda maka akan kuguncang panggung pertunjukan, berikan aku sepuluh pemudi, maka akan ku buat girlband. Biarkan aku selfie dengan gayaku maka aku ada dan mengguncang dunia. (*)
Sumber :
A.Setyo Wibowo & Majalah Driyakarya, Filsafat Eksistensialsme. 2011
Roy Jakson, Friedrich Nietszche. 2015 terjh.
*Penulis adalah Abdul Salman, Mantan Presiden BEM FIP UNM Periode 2013-2014