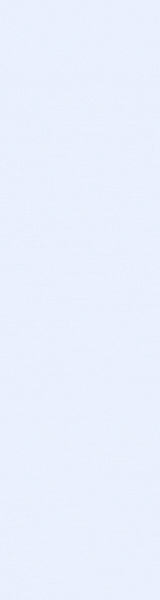PROFESI-UNM.COM – Di sebuah sekolah, antrean orang tua yang hendak mendaftarkan anaknya mengular sejak pagi buta. Mereka menenteng berkas pendaftaran, berharap diterima di sekolah yang katanya “favorit” itu. Sementara di tempat lain, di sebuah sekolah yang bisa menampung seratus murid, hanya kedatangan sebelas pendaftar.
Fenomena ini bukan lagi hal mengejutkan sebenarnya, terutama bagi sekolah yang setiap tahun menerima kenyataan yang sama, sepi peminat. Kepala sekolah hingga para guru di sana, tak berani pasang target muluk-muluk, yang penting ada. Setiap memasuki tahun ajaran baru, peta pendidikan kita mempertontonkan ketimpangan: sekolah yang penuh sesak dan sekolah yang kesepian.
Kenyataan ini jelas mengundang pertanyaan: mengapa sebuah sekolah begitu diburu, sementara yang lain kurang dilirik? Apakah hanya karena pelabelan sebagai sekolah “favorit”, yang mungkin juga tak mereka tahu sebabnya, sekadar kabar dari mulut ke mulut. Ataukah ada pertimbangan sistemik yang lebih inti, soal persepsi, fasilitas, hingga kualitas.
ADVERTISEMENT
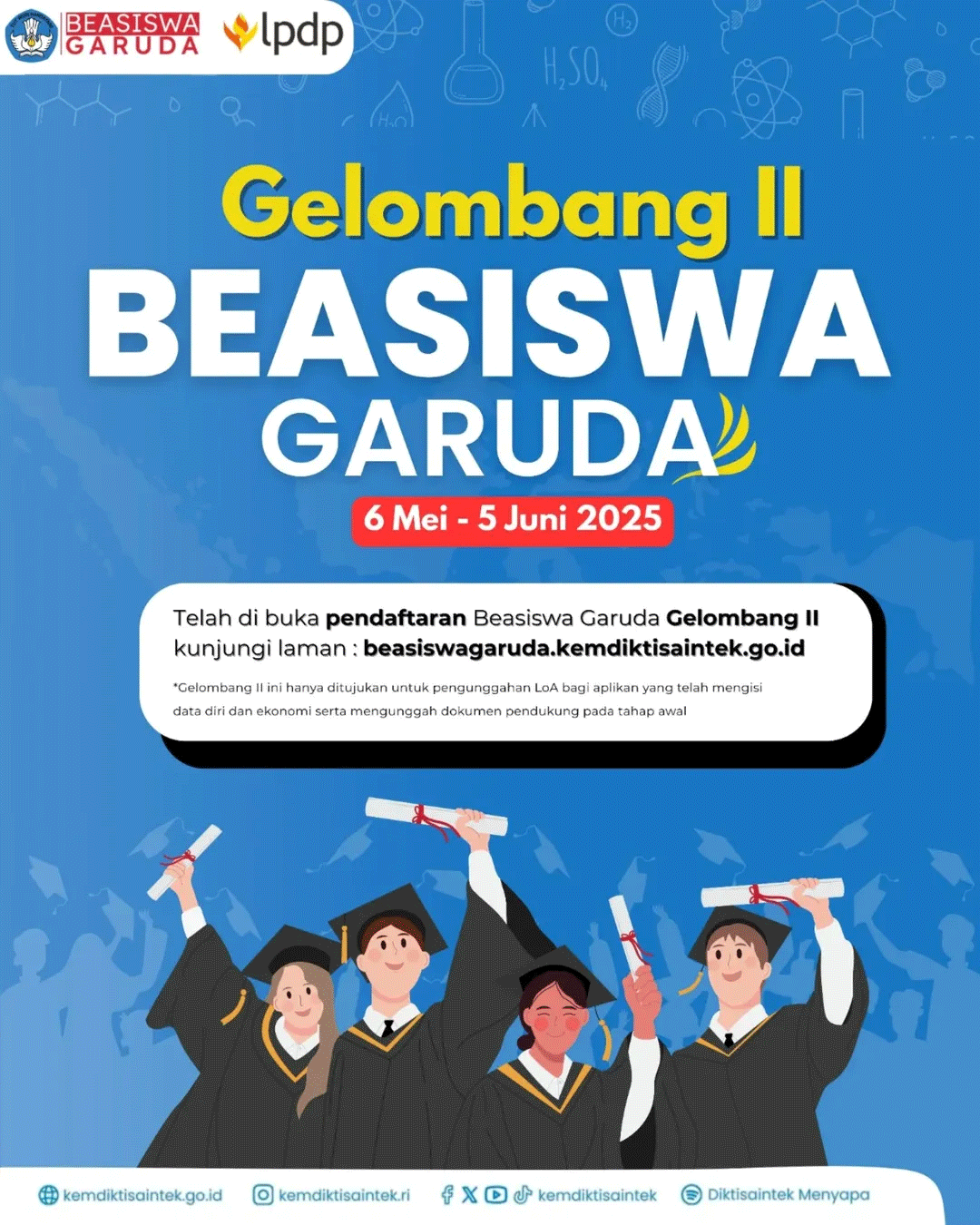
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam urusan mendaftarkan anak sekolah, barang tentu orang tua akan memilah sekolah-sekolah, yang antara lain punya reputasi akademik mumpuni, punya alumni sukses di mana-mana. Atau, memilih sekolah dengan label favorit.
Percayalah, saat orang tua menggandeng anak kecilnya mendaftar masuk sekolah, sebenarnya mereka tidak hanya mendaftarkan anaknya di sekolah itu. Mereka sedang membeli harapan. Dan harapan itu, tampaknya hanya tersedia di tempat-tempat tertentu.
Polemik tahunan ini, membuat pemerintah tampaknya berang juga. Sehingga pemerintah pada kisaran tahun 2016 sampai 2017 mengambil langkah pemerataan pendidikan melalui kebijakan zonasi, dalam penataan sistem penerimaan peserta didik baru, yang dilakukan dengan pendekatan layanan berbasis geospasial.
2025, apa masalah pada penerimaan peserta didik baru selesai dengan adanya zonasi? Tidak. Kebijakan ini belum menyelesaikan akar masalah. “Pemerataan peserta didik” tanpa melakukan “pemeratan kualitas sekolah” terlebih dulu, adalah langkah konyol.
Zonasi seharusnya menjamin anak bersekolah dekat rumah, tapi tanpa kualitas yang setara, ia hanya jadi sistem paksa yang kehilangan legitimasi. Mulai dari kasus jual beli kursi, manipulasi data domisili, hingga polemik titip menitip anak di sekolah, adalah sederet kasus yang mewarnai pemberlakuan kebijakan ini. Benturan batin terjadi, tatkala harus memilih antara menjalankan peraturan atau memilih sekolah terbaik untuk masa depan anak.
Ketimpangan jumlah pendaftar hanyalah gejala permukaan. Yang lebih penting adalah penyakit yang menggerogoti sistem: kebijakan yang belum sepenuhnya adil, ketimpangang fasilitas, hingga kualitas guru yang tidak merata. Semua ini bermuara pada satu hal: preferensi orang tua dalam memilih sekolah untuk anaknya. Dalam kondisi seperti ini, pilihan menjadi bukan soal jarak, tetapi soal kepercayaan.
Upaya-upaya pemerintah menghapus term ‘’sekolah favorit” layak diapresiasi, namun, dalam praktiknya seringkali kontraproduktif. Ketika kualitas antarsekolah belum setara, menghapus label “favorit” tidak serta merta menghapus kenyataan sosial yang mendasarinya.
Pemerintah boleh saja menghapus istilah favorit yang selama ini tertempel di sekolah. Tapi label itu tidak pernah benar-benar mati, ia tetap hidup di benak orang tua murid, dalam obrolan di grup-grup WhatsApp. Favoritisme tak mesti tertulis di papan pengumuman, ia tumbuh subur di ruang persepsi.
Ketika jumlah peserta didik minim, konsekuensinya tidak hanya berdampak pada ruang kelas yang sunyi. Terbatasnya Jumlah peserta didik bisa menyebabkan jam mengajar guru berkurang, dan dalam konteks tertentu ini langsung memengaruhi poin sertifikasi dan tunjangan profesi.
Guru yang tidak memenuhi beban minimal 24 jam pelajaran per pekan bisa kehilangan hak atas tunjangan sertifikasi, sesuatu yang selama ini menjadi kompensasi profesional mereka. Akibatnya, guru-guru mulai mencari tambahan jam di sekolah lain, bahkan ada yang rela mengajar di dua atau tiga sekolah sekaligus, untuk sekadar memenuhi syarat administrasi.
Tak hanya guru, sekolah secara kelembagaan pun turut terdampak. Kurangnya peserta didik membuat biaya operasional menjadi timpang: dana BOS yang berbasis jumlah murid otomatis menurun. Dampak lain misalnya, kegiatan sekolah menjadi terbatas, dan fasilitas berupa kelas menjadi tak terpakai.
Dalam jangka panjang, citra sekolah menjadi merosot: sekolah yang sepi murid dianggap sekolah buruk, meskipun mungkin kualitas pengajarnya tak kalah baik. Hal ini menciptakan lingkaran setan: semakin sedikit murid, semakin kecil sumber daya. Semakin kecil sumber daya, semakin rendah daya tariknya. Sehingga yang maju makin maju, yang tertinggal makin sulit mengejar.
Dibutuhkan komitmen nyata untuk menyamakan kualitas. Memperbaiki sarana di sekolah yang tertinggal, sebaran guru yang tepat sasaran, dan menjadikan setiap sekolah, tak peduli di mana letaknya, sebagai ruang yang layak, bagi anak-anak untuk bermimpi. Karena setiap anak, di mana pun ia tinggal, berhak merasakan pendidikan yang setara, bukan sekadar disalurkan agar angka terlihat bagus dalam laporan.
Tahun ajaran baru seharusnya disambut dengan suka cita. Namun, lain hal dengan sekolah-sekolah “pinggiran”, tahun ajaran baru justru datang membawa kegelisahan: apakah ada cukup murid tahun ini? Akankah satu kelas penuh? Akankah sekolah kembali dipercaya? Tahun ajaran baru bagi mereka bukan perayaan. Ia adalah ujian keberadaan. (*)
*Penulis: Wahyu Hidayat, Mahasiswa PPG Prajabatan UNM