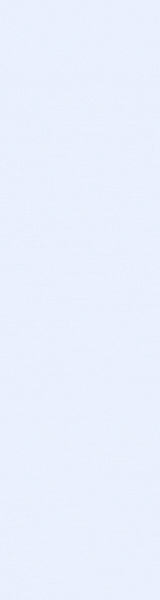PROFESI-UNM.COM – Kasus pelecehan seksual kembali menyeruak di Universitas Negeri Makassar (UNM). Terduga pelaku merupakan salah satu Ketua Lembaga Kemahasiswaan (LK) di Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS). Dari kronologi yang beredar, kekerasan seksual tersebut terjadi di luar kampus dimana korbannya merupakan junior dari pelaku.
Data yang dihimpun Estetikapers pada 18 April – 14 Juni 2021, menunjukkan sebanyak 38 kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan FBS. Ada 4 kasus dilakukan oleh oknum dosen, 31 kasus dilakukan oleh mahasiswa dan sisanya tidak merincikan pelaku.
Namun jumlah korban bisa saja jauh lebih besar jika semua penyintas ingin berbicara. Tingginya angka kekerasan seksual tidak mengubah paradigma pimpinan UNM. Kampus masih saja tidak melihat kekerasan seksual sebagai masalah genting yang perlu segera disikapi.
ADVERTISEMENT
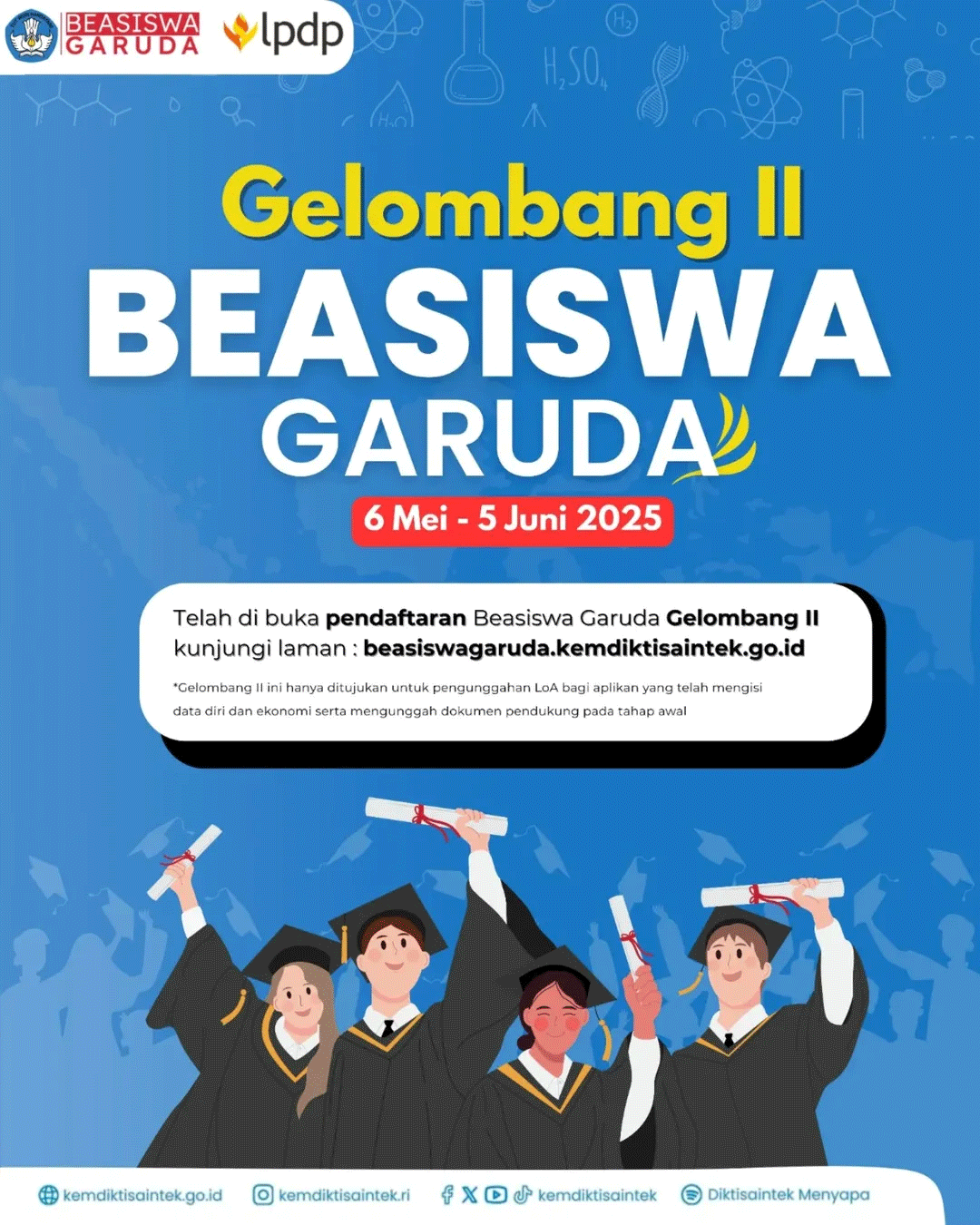
SCROLL TO RESUME CONTENT
Padahal Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, telah membukakan jalan selebar-lebarnya agar kampus dapat menyusun pedoman dan membentuk satuan tugas (satgas). Dalam permen tersebut, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilaksanakan dengan prinsip ‘jaminan ketidak berulangan’ sebagaimana yang tercantum pada pasal 3 huruf h.
Jika mengamati kondisi UNM hari ini, ketimpangan sangat mudah dideteksi, dimana kasus kekerasan seksual masih saja terus berulang. Meski begitu, UNM sepertinya tidak peduli dan tidak mau tahu. Sikap tersebut menjadikan UNM sebagai institusi pendidikan yang terus memproduksi kekerasan seksual. Tidak heran, setiap kasus yang muncul, menguap begitu saja.
Beberapa LK dan kelompok kolektif lainnya pernah melakukan aksi protes terkait ketidakhadiran kampus dalam problem ini. Namun lagi, ditanggapi dingin oleh rektorat. Adanya kondisi dimana Rektorat cenderung menormalisasi situasi, seakan-akan kampus aman-aman saja dan mahasiswanya bahagia. Kenyataan ini menjadi momok menakutkan bagi kelompok rentan, terutama korban. Kasus tidak pernah betul-betul berakhir dengan mengedepankan kepentingan korban. Sementara korbanlah yang mengalami trauma berat. Rasa ‘tidak bersalah’ kampus, harusnya membuat siapa saja marah, termasuk memantik protes mahasiswa yang lebih besar. Sebab kekerasan seksual pada dasarnya bukan hanya melanggar HAM, tetapi juga merusak citra Pendidikan dan institusi UNM sebagai kampus yang dikenal modern dan berkemajuan.
Harus diakui, UNM sangat ‘terbelakang’ dibanding kampus lain dalam hal penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. Universitas Hasanuddin (UNHAS) telah memiliki Satuan Tugas (satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), lengkap dengan Peraturan Rektornya. Selanjutnya, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) telah membentuk Lembaga Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Rektor. Sementara UNM masih terus jalan ditempat.
Dengan mutu Pendidikan sangat baik (akreditasi A), UNM tidak bisa berbuat banyak. UNM belum mampu membentuk satgas PPKS. Belum adanya Satgas dan Peraturan Rektor Tentang PPKS, membuat kepastian hukum turut abu-abu. Hak korban mendapatkan pendampingan, perlindungan serta pemulihan tidak akan pernah terwujud.
Alhasil, banyak korban kekerasan seksual yang tidak mendapatkan keadilan. Dirana penanganan, kasus-kasus kekerasan seksual tidak sedikit diselesaikan secara kekeluargaan (damai) atau dengan sanksi ringan atas pelaku. Sementara di pihak keluarga korban, cenderung memilih menghindari resiko lebih besar, sehingga tidak menempuh jalur hukum dengan sungguh-sungguh. Tidak sedikit, korban kekerasan seksual justru mendapat intimidasi, tekanan, dan ancaman. Kondisi ini membuat keluarga dan korban seakan tidak punya pilihan lain, selain pasrah menerima perlakuan tidak manusiawi.
Paradigma bahwa kekerasan seksual adalah ‘ib Universitas’ seringkali dijadikan dalih untuk menutup-nutupi tiap kasus. Kampus memilih menyelamatkan nama baik institusi ketimbang masa depan korban. Dari sini, kita melihat UNM tidak memiliki komitmen memberikan ruang aman bagi seluruh civitas akademiknya. Kampus cenderung melihat masalah kekerasan seksual diluar dari kewajiban dan tanggung jawabnya. UNM seolah-olah tidak memahami urgensi dari Permendikbud Nomor 30, meskipun memiliki 101 guru besar.
Hemat penulis, dengan fakta-fakta diatas, UNM saat ini dalam status ‘tidak melaksanakan’ perintah dalam permendikbud. Pertama, UNM tidak melaksanakan kewajibannya melakukan upaya pencegahan kekerasan seksual sebagaimana isi Pasal 6 ayat 3 huruf a,b, dan c, tentang kewajiban kampus melakukan upaya pencegahan melalui pembelajaran, tata Kelola, serta budaya komunitas civitas akademik. Sikap bodo amat terhadap kekerasan seksual, tidak hanya di level petinggi universitas, namun juga merembet ke tingkat prodi/jurusan, hingga fakultas. Birokrat memilih sibuk memperbaiki citra institusi dan personal, dibanding memikirkan keselamatan korban. Belum adanya satgas, peraturan rektor dan pedoman pokok lainnya terkait PPKS, maka sudah sepantasnya UNM dijatuhi sanksi tegas. UNM begitu lamban dalam menindaklanjuti Permendikbud Nomor 30, padahal telah ditetapkan pada 31 Agustus 2021 (sekitar 1 tahun yang lalu). Atas dasar tersebut, sanksi berlapis mesti dijatuhkan pada UNM.
Kedua, pasal 19 menegaskan bahwa perguruan tinggi yang tidak melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dikenai sanksi administratif berupa ‘penghentian’ bantuan keuangan atau bantuan sarana prasarana hingga penurunan tingkat ‘akreditasi’. Ketiga, pasal-pasal di atas diperkuat pasal 55 bahwa pemimpin perguruan tinggi yang tidak melaksanakan pemantauan dan evaluasi pencegahan dan penanganan PPKS, maka diberi sanksi teguran tertulis, hingga ‘pemberhentian’ dari jabatan pemimpin perguruan tinggi.
Lalu apakah UNM sebagai institusi Pendidikan dapat benar-benar disanksi? Siapa yang berani menjatuhkan sanksi pada pimpinan UNM? Atau mungkin keduanya kebal hukum? Situasi kampus yang tidak aman membuktikan bahwa kinerja rektorat masih pada level ‘setengah hati’. Selain tidak melaksanakan amanat Permendikbud PPKS, UNM juga gagal menjalankan amanat Undang-undang. Konstitusi negara menegaskan bahwa tiap pelaksana Pendidikan berkeharusan memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan.
Di UNM, setiap korban kekerasan seksual tidak memperoleh pendampingan, perlindungan, apalagi layanan pemulihan. Itulah mengapa kampus UNM layak diberi label sebagai perguruan tinggi negeri yang tidak ‘manusiawi’ serta layak dikenakan sanksi berlapis. (*)
*Akbar, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar
*Tulisan ini telah terbit di tabloid edisi 262