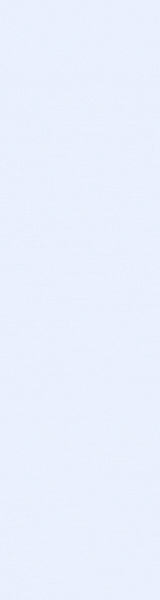PROFESI-UNM.COM – Dewan perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Namun ada beberapa pasal yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Seperti pasal 218 dalam KUHP mengenai kritik kepada Presiden dan Wakil Presiden, pasal 219 tentang penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden dan wakil presiden, pasal 240-241 mengenai penghinaan pemerintah di media sosial, dan 256 mengenai pembatasan mengkritik dan menyuarakan aspirasi rakyat.
Divisi dokumentasi dan riset lembaga bantuan hukum (LBH), Salman mengatakan kebebasan berpendapat adalah hak semua orang. kalau di pasal itu memerlukan izin, artinya dalam konteks hak asasi manusia (HAM) tidak lagi sebagai bentuk hak karena pada dasarnya hak asasi itu tidak dibatasi dengan ketentuan.
“Seharusnya kan tidak dibatasi seperti itu, karena kebebasan berekspresi itu haknya setiap individu. Adapun, misalkan hal ini dalam konteks orang membuat macet. Disatu sisi harus ada pembatasan aksi demonstrasi, makanya itu kenapa dibatasi sampai jam tujuh malam untuk memastikan agar hak orang lain terpenuhi juga,” katanya.
ADVERTISEMENT
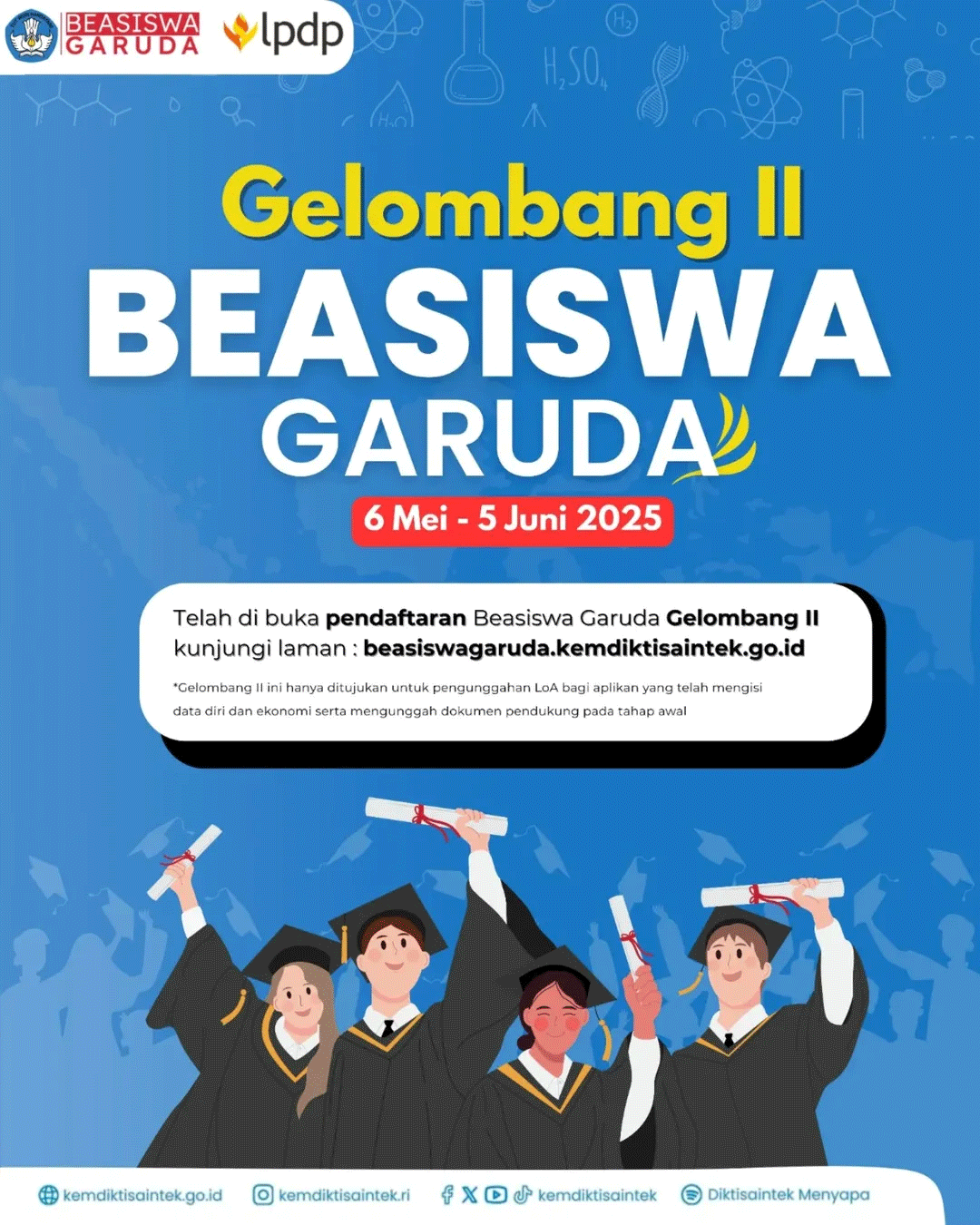
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lanjut, Salman mengungkapkan dalam konteks pasal tersebut sebenarnya bukan melarang tapi soal isu kebebasan berekspersi secara kontekstual itu mengisyaratkan untuk mengajukan izin saat mengadakan demonstrasi jika tidak disetujui artinya ia bisa disebut ilegal.
“Jika ilegal kan bisa saja polisi berpotensi melakukan diskriminalisasi itulah mengapa dikritisi pembahasannya bukan soal isu kebebasan berekpresi tapi ini soal menyatakan pendapat, misalnya mungkin menghina presiden” ungkapnya.
Lebih lanjut, menurut Salman hal itu malah bagus kita menyampaikan kepada pihak keamanan, karena tugas dan fungsinya memastikan penegakan. Salman juga menyinggung terkait konteks mengkritik dan menghina presiden dan wakil presiden. Ia mengungkapkan bahwasanya sulit untuk membedakan antara mengkritik dan menghina jika masyarakat juga masih kesulitan untuk memahami indikator harkat dan martabat presiden. Harkat dan martabat presiden didasarkan oleh perbedaan pola hidup dan kesopanan berbahasa antara pemerintah dengan masyarakat menjadi masalah utama. Bahasa yang dimaksud disini yaitu ketika masyarakat sudah tidak memiliki pilihan lain kecuali memasukkan emosinya kedalam kritikan yang dilontarkan, membuatnya terdengar sebagai hinaan atau cemohan oleh pemerintah yang tidak terbiasa mendengar istilah kasar tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka.
‘’Misalkan dalam suatu waktu dia (masyarakat) punya kesempatan ini (berpendapat) toh dia tidak punya Bahasa atau kalimat menguraikan data, dia hanya mengatakan begini, sialan ini presiden kita. Karena tidak adanya bahasa lain yang mungkin dia tau untuk dia gunakan jadi hanya bahasa kesehariannya dia pake. Yah itu beda menghina, yah misalnya ini Jokowi ini mukanya kayak tai nah menghina itu. beda konteks kalau misalkan presiden ini sifatnya kayak tai, kita kan tidak menghina orangnya yang dilarang itu menghina individunya, bukan jabatannya atau bukan institusinya,’’ jelasnya.
Sama halnya dengan yang telah dia sebutkan sebelumnya, pengadaan undang undang yang melindungi harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, nampaknya tidak adil jika tidak disertai dengan undang-undang yang sama untuk melindungi rakyat. Apabila undang-undang tersebut resmi disahkan, tentu akan mencederai nilai-nilai demokrasi. (Tim)
*Tulisan ini telah terbit di tabloid edisi 262