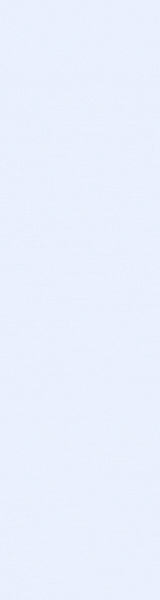PROFESI-UNM.COM – pungli merupakan salah satu tindakan melawan hukum yang diatur dalam undang-undang
nomor 31 tahun 1999 junto. Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang pemberantasan
tindak pidana korupsi. Pungutan liar termasuk tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar
biasa (extra ordinary crime) yang harus diberantas. Komitmen pemerintah untuk melakukan berbagai
reformasi terus dilakukan. Setelah mengeluarkan hukum melakukan pungli terdapat di Pasal 13 UU
PTKP yang menyatakan bahwa setiap orang yang memberikan, atau menjanjikan uang atau barang
kepada pihak yang melakukan pungutan liar, juga dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama 5
tahun, dan denda paling banyak Rp250 juta.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) merupakan pengadilan yang memiliki kewenangan, untuk
mengadili tindak pidana korupsi, termasuk tindak pidana pungutan liar. Namun, meskipun ada hukum
yang melarang pungutan liar, praktik ini masih terjadi di banyak sektor dan bidang di Indonesia.
Upaya paket reformasi “Setop Pungli” diharapkan tidak hanya memulihkan kepercayaan publik,
memberikan keadilan dan kepastian hukum. Namun juga harus mampu berdampak langsung terhadap
perbaikan kinerja perekonomian ke depan. Pasalnya, berdasarkan World Economic Forum peringkat
daya saing Indonesia semakin memburuk.
ADVERTISEMENT
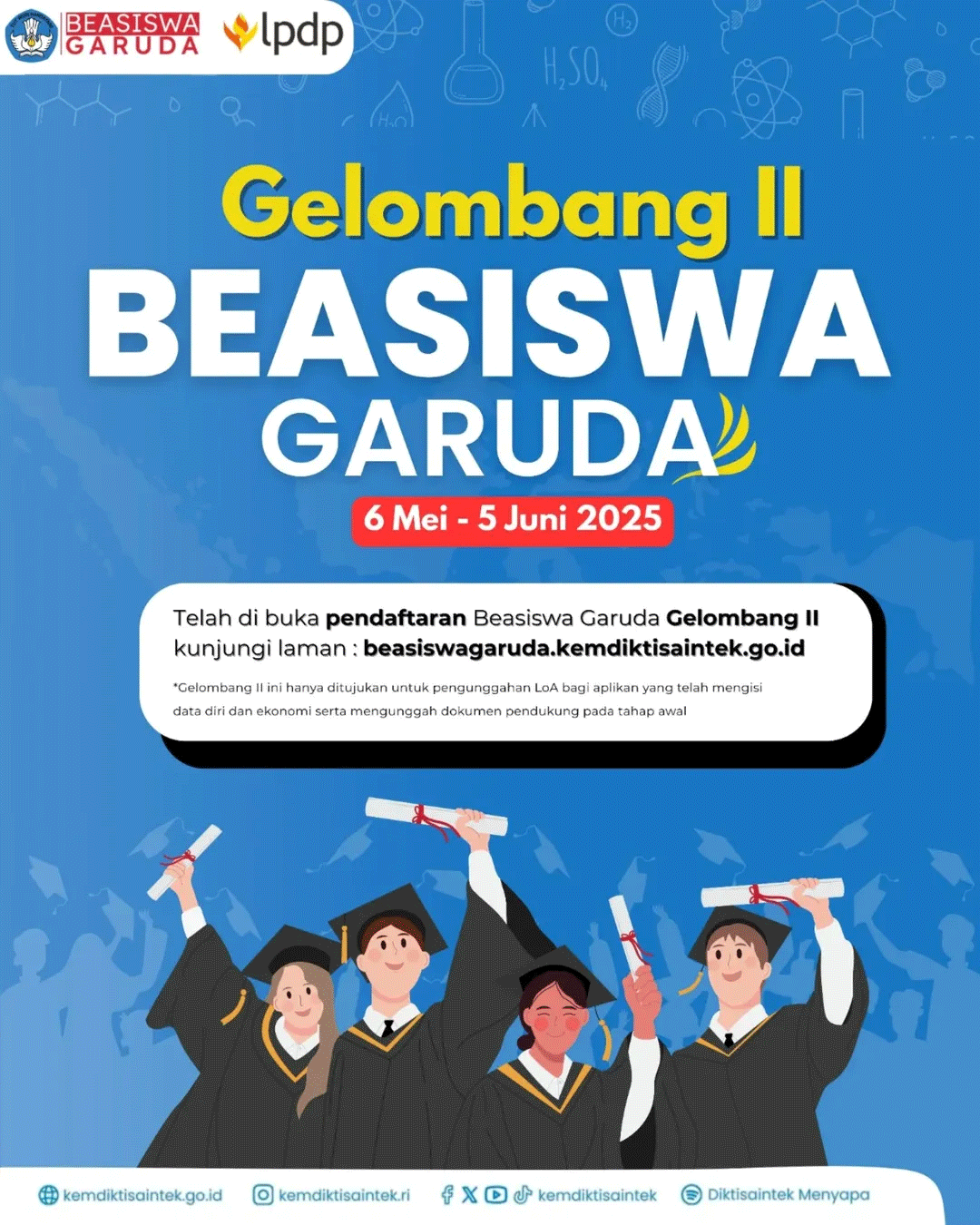
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu aspek yang mengalami penurunan peringkat adalah aspek kelembagaan. Artinya efektifitas
kerja birokrasi justru semakin menurun, yang akhirnya menimbulkan ekonomi berbiaya tinggi (high
cost economy). Hal ini terjadi dikarenakan berbagai sektor pelayanan publik, masih diwarnai berbagai
praktik pungli secara terstruktur, sistematis, dan massif. Pungli masih menjadi salah satu penyakit akut
yang menjangkit birokrasi pemerintahan sejak zaman Penjajahan.
Kultur nepotisme dan koneksi di lingkungan birokrasi, menjadi faktor penting dalam terjadinya praktik
pungli. Hal ini karena orang yang memiliki koneksi atau jaringan yang luas di lingkungan birokrasi, dapat
memanfaatkan posisi atau jabatannya untuk mengambil keuntungan pribadi, termasuk melalui pungli.
Ketika sebuah sistem membiarkan orang untuk memanfaatkan posisi atau jabatan mereka untuk
kepentingan pribadi, maka hal tersebut akan menjadi sangat mudah dilakukan.
Padahal, mestinya pelayanan terhadap hak-hak masyarakat merupakan kewajiban dan tanggung jawab
pemerintah sebagai penyedia layanan publik. Namun, karena pelayanan dimaknai sebagai
kewenangan sehingga dianggap sah jika berimplikasi menimbulkan beban biaya.
Akibatnya, kebiasaan menyalahgunakan wewenang sampai praktik transaksional kepentingan
ekonomi, dianggap hal lumrah. Pungli menghampiri hampir seluruh level pelayanan publik, mulai level
individu sampai dengan korporasi. Dari mengurus kartu keluarga, KTP, SIM, paspor sampai ketika
korporasi mengurus izin memulai usaha maupun sekedar memperpanjang izin usaha.
Munculnya berbagai praktik pungutan liar atau uang sogokan, uang pelicin, salam tempel dan lain-lain
tentu terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak. Harus diakui, masih banyak masyarakat yang ingin
hasil instan.
Namun, persoalannya masyarakat dihadapkan pada ketidak pastian, ruwetnya dan berbelit-belit
prosedur birokrasi pelayanan. Akibatnya, untuk memperlancar urusan masyarakat dipaksa menyerah
dan permisif terhadap praktik pungli.
Apalagi dari sisi para pelaku usaha tentu akan mengkalkulasi efisiensi. Sejumlah biaya pungli akan rela
dikeluarkan agar dapat membeli kepastian waktu. Daripada harus mengikuti standar pelayanan yang
sekalipun tanpa biaya, namun dengan waktu yang tidak pasti, keputusan menyuap sering dianggab
menjadi rasional.
Hal yang terpenting adalah upaya mengikis praktik dan budaya pungli secara kongkrit. Agar berbagai
sumber penyebab tingginya ekonomi berbiaya tinggi dapat secara persisten dikikis. Untuk itu, solusinya
harus dimulai dari akar dan sumber persoalannya.
Bagaimanapun, timbulnya praktik pungli berawal dari adanya kebutuhan terhadap pelayanan dari
pihak pemberi layanan. Untuk itu, konsep dasar pemberian pelayanan publik harus dikembalikan
menjadi kewajiban pemerintah dan hak dari masyakat.
Karenanya, berbagai fungsi pelayanan publik yang harus disediakan pemerintah mestinya tidak perlu
dimasukkan dalam sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, tentu konsistensi juga
harus diterapkan. Artinya, setelah masyarakat menerima dan menikmati pelayanan publik tentu harus
patuh membayar pajak, baik secara pribadi maupun korporasi.
Sebagai ilustrasi, jika berbagai kemudahan perizinan dapat disederhanakan dengan pelayanan yang
terintegrasi dengan menggunakan teknologi, maka akan ada kepastian bagi pelaku usaha untuk
berinvestasi. Dengan demikian iklim investasi akan lebih kondusif, kontribusi pajak dari PPh, PPn, PBB
dan pajak lainnya akan semakin meningkat.Jika penerimaan pajak meningkat, tentu ruang untuk
meningkatkan renumerasi dan gaji PNS juga akan semakin tinggi. Hasil akhirnya berbagai pungli, secara
sistemik dapat dikikis dan diberangus. (*)
*Penulis: Nurul Husna Asrah, mahasiswa Program Studi Pascasarjana Ilmu Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar