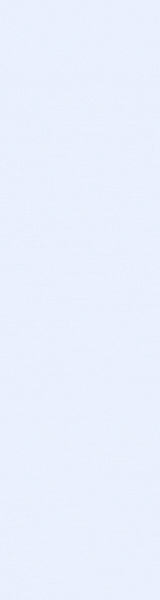PROFESI-UNM.COM – Ketidakselarasan antara birokrat dan mahasiswa yang terus bersitegang memperdebatkan kesiapan transformasi status UNM menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) adalah isu panas yang sangat menarik untuk dibahas.
Menyelisik dinamika status UNM saat periode sebelum tahun 2019, Kampus Pinisi merupakan salah satu kampus berstatus Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN-Satker) yang dalam perjalanannya cukup banyak menorehkan prestasi. Misalnya dengan meraih akreditasi A pada tahun 2017 serta dianugerahi sebagai PTN-Satker Terbaik I se-Indonesia berturut-turut pada tahun 2017-2018.
UNM yang semakin haus prestasi, menunjukkan progresivitas dalam membenahi tata kelola kampus yang semakin baik, memutuskan beralih status sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) pada tahun 2019 (sampai saat ini). Hingga periode ini, UNM masih tetap eksis meraih penghargaan nasional bahkan pernah masuk 30 besar daftar perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Dengan capaian prestisius tersebut, Rektor UNM, Husain Syam dengan percaya diri mengusulkan UNM menjadi PTN-BH.
ADVERTISEMENT
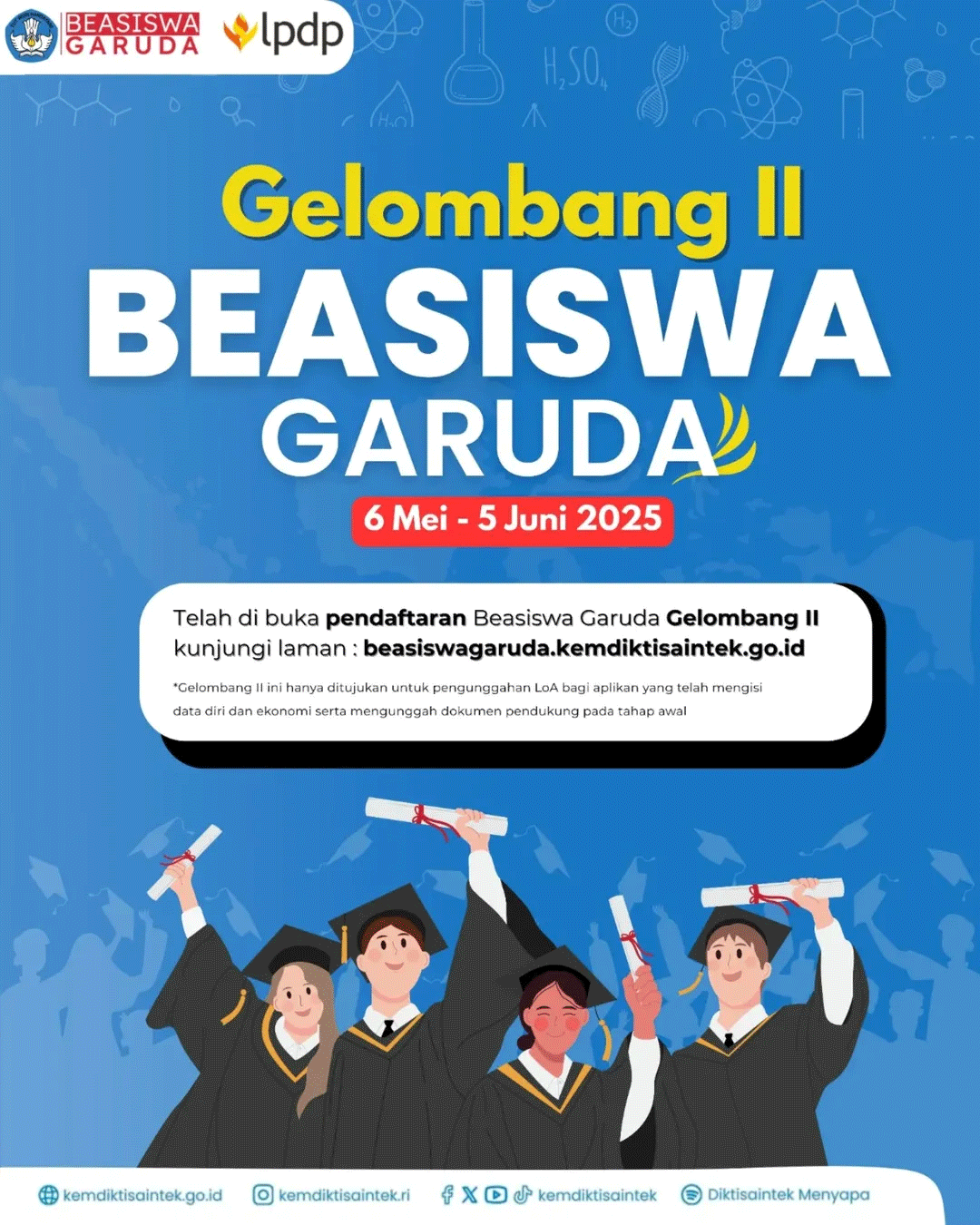
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perlu juga kita ketahui, untuk menjadi PTN-BH tumpukan prestasi dan penghargaan tidaklah cukup, tapi UNM wajib memenuhi syarat wajib yang diatur dalam Permendikbud No. 4 tahun 2020 yaitu; a. menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu; b. mengelola organisasi PTN berdasarkan prinsip tata kelola yang baik; c. memenuhi standar minimum kelayakan finansial; d. menjalankan tanggung jawab sosial; e. berperan dalam pembangunan perekonomian. Khusus dalam tulisan ini, penulis lebih terfokus pada pembahasan poin a dan c, serta membahas poin lainnya secara umum.
Untuk poin a, dalam memenuhi persyaratan tersebut perguruan tinggi harus memiliki paling sedikit 60% (enam puluh persen) program studi dengan peringkat akreditasi unggul. Dibenturkan dengan kondisi UNM saat ini yang program studi di jenjang sarjana dan vokasi hanya mencapai 19% dengan rincian hanya 23 program studi yang terakreditasi unggul dari 120 jumlah program (l2mp.unm.ac.id). Sementara itu, secara keseluruhan hanya terdapat 15% program studi di jenjang S1-S3 dengan rincian hanya 24 program studi terakreditasi unggul dari 157 program studi (pddikti.kemdikbud.go.id). Dengan kondisi seperti ini, sudah jelas UNM tidak mampu memenuhi syarat yang dimaksudkan.
Namun, dalam situasi seperti ini bukan berarti tidak bisa diakali. Kuatnya keinginan para birokrat untuk mengubah status ke PTN-BH bisa saja mengamini segala cara untuk menyukseskan ambisi tersebut. Untuk beberapa kasus, manipulasi pengisian borang re-akreditasi adalah pelanggaran umum yang kerap terjadi dalam dunia pendidikan agar program studi maupun perguruan tinggi bisa mendapatkan peringkat akreditasi yang lebih baik.
Hal seperti ini akan berimbas kepada ekspektasi mahasiswa maupun calon mahasiswa dengan merasakan kondisi secara langsung akibat upaya komersialisasi pendidikan yang tidak mengutamakan kualitas (ketidaksesuaian sarana dan prasarana, metode perkuliahan, dan rasio dosen). Disebabkan oleh pergeseran budaya akademis kampus yang lebih mementingkan pengakuan dan menyampingkan tujuan perguruan tinggi yang diamanatkan oleh konstitusi dan perundang-undangan.
Tidak berhenti di situ, perkenaan tata kelola pendidikan yang baik kurang tercerminkan pada sebagian besar fakultas atau program studi yang ada di UNM. Hal tersebut dapat dilihat dari kesiapan sarana dan prasarana penunjang wajib seperti kapasitas kelas yang tidak sebanding dengan jumlah mahasiswanya, mengakibatkan beberapa perkuliahan yang seharusnya dilakukan secara luring malah dijalankan secara daring.
Selanjutnya, Undang-undang Pendidikan Tinggi Nomor 12/2012 serta Peraturan Pemerintah Nomor 4/2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi. Melalui undang-undang ini ditegaskan bahwa rasio ideal antara dosen dan mahasiswa adalah 1:20 untuk Ilmu Eksakta dan 1:30 untuk Ilmu Sosial. Sekarang coba lihat realitas faktualnya seperti apa? dari tahun ke tahun penerimaan mahasiswa baru di UNM terus mengalami peningkatan tapi sayangnya penambahan tenaga pendidik dan ruang kelas enggan diberlakukan.
Terkait poin c, mengenai kemampuan menggalang dana selain dari biaya pendidikan dari mahasiswa merupakan suatu hal yang pesimis dengan melihat kondisi badan usaha UNM saat ini. Badan usaha yang dibentuk oleh UNM seperti Hotel (La Macca), Koperasi, Toko, Bengkel, serta bentuk layanan jasa dan produk lainnya hanya memberikan kontribusi kecil yang tidak sebanding dengan biaya pendidikan dari mahasiswa. Kondisi tersebut mengasumsikan bahwa ada kemungkinan terjadinya komersialisasi pendidikan, pihak kampus berorientasi menjaring masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas. Akhirnya kelulusan calon mahasiswa bukan karena kompetensi intelektual, tetapi persaingan kompetensi kekuatan ekonomi, di mana hal ini dianggap legal sehingga dibiarkan oleh pemerintah berdasarkan perluasan otonomi kampus berstatus PTN-BH.
Pada dasarnya, secara normatif tujuan PTN-BH untuk meningkatkan kualitas kampus merupakan ide yang mulia. Otonomi akademik dan non akademik memberikan kampus leluasa bergerak dan berkembang. Faktanya, tidak semudah membalik telapak tangan. Jika otonomi menjadi alasan kualitas, seharusnya banyak kampus swasta yang lebih berkualitas dan maju dibandingkan PTN.
Perlu diketahui bahwa status PTN-BH bukan satu-satunya upaya dalam meningkatkan kualitas kampus. Namun, akumulasi kepemimpinan, sumber daya manusia, fasilitas, dan budaya kerja yang baik adalah indikator nyata yang bisa membawa UNM semakin berjaya. Apapun status kampus akan berkualitas jika ada di tangan rektor dengan kepemimpinan yang transformatif, visioner, demokratis, dan berjiwa wirausaha.
Hal yang penulis takutkan di tengah maraknya kampus berstatus PTN-BH adalah ketika dosen atau ilmuwan kita berubah profesi menjadi pengusaha. Dosen disibukan dengan mencari proyek-proyek kerja sama dibanding mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengabdian pada masyarakat. Para pejabat kampus berkerumun dan berdebat membicarakan untung-rugi, bukannya adu pemikiran untuk melahirkan ilmu dan inovasi baru.
Di samping itu, otonomi keuangan membuka celah untuk korupsi. Misalkan upaya bentuk kerja sama dengan pengusaha membuka peluang KKN jika para pejabat birokrasi tidak amanah dan jujur. Ditambah kondisi UNM saat ini yang sangat tertutup kepada mahasiswanya untuk menerapkan prinsip akuntabilitas ke lembaga internal mahasiswa sebagai mitra pengembangan dan pengawasan kinerja kampus. Padahal, prinsip transparansi dan akuntabilitas adalah semangat yang dikandung UU Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 78 yang menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi (PT) harus melaporkan kegiatan kampus baik akademik maupun non akademik kepada masyarakat.
Otonomi pengelolaan keuangan serta kemampuan birokrat dalam bidang pengembangan usaha dan penggalangan dana adalah tantangan yang nyata. Ketika hal tersebut tidak dijalankan dengan baik maka bisa saja biaya pendidikan semakin mahal, sehingga masyarakat golongan ekonomi ke bawah yang memiliki impian untuk melanjutkan pendidikannya menjadi korban dan mengubur impian tersebut dengan tragis.
Akhir tulisan, berdasarkan hemat analisis penulis bahwa UNM belum siap untuk menyandang status PTN-BH. Mengenai angan-angan UNM mengejar status tersebut adalah hal yang tidak pantas untuk diperjuangkan mati-matian. UNM seharusnya berani berbeda sebagai kampus yang mewadahi secara terbuka dan menjamin akses pendidikan yang layak seluas-luasnya bagi seluruh golongan masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan bukan hanya untuk golongan tertentu, sebagaimana halnya pendidikan adalah hak yang harus dipenuhi dan dijamin oleh negara kepada masyarakatnya. (*)
*Penulis adalah Muh. Riyadh Ma’arif, Ketua Komisi Pendidikan Maperwa Universitas Negeri Makassar periode 2023.