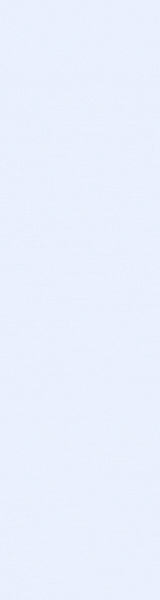PROFESI-UNM.COM- Dalam beberapa tahun terakhir, istilah seperti overthinking, anxiety, depresi, hingga ADHD sering muncul di linimasa media sosial. Banyak pengguna, terutama generasi muda, mulai mengidentifikasi diri mereka berdasarkan informasi yang mereka temukan di TikTok, X, atau Instagram. Fenomena ini dikenal sebagai self-diagnose, yaitu tindakan menilai atau mendiagnosis kondisi mental diri sendiri tanpa melalui tenaga profesional.
Tren ini muncul karena dua hal: akses informasi yang melimpah dan minimnya edukasi formal tentang kesehatan mental. Akibatnya, banyak pengguna yang merasa “tercerahkan” setelah menemukan konten psikologi yang relatable. Mereka mulai mengaitkan gejala yang dialami dengan gangguan tertentu hanya berdasarkan konten singkat berdurasi satu menit.
Antara Edukasi dan Bahaya Mispersepsi
ADVERTISEMENT
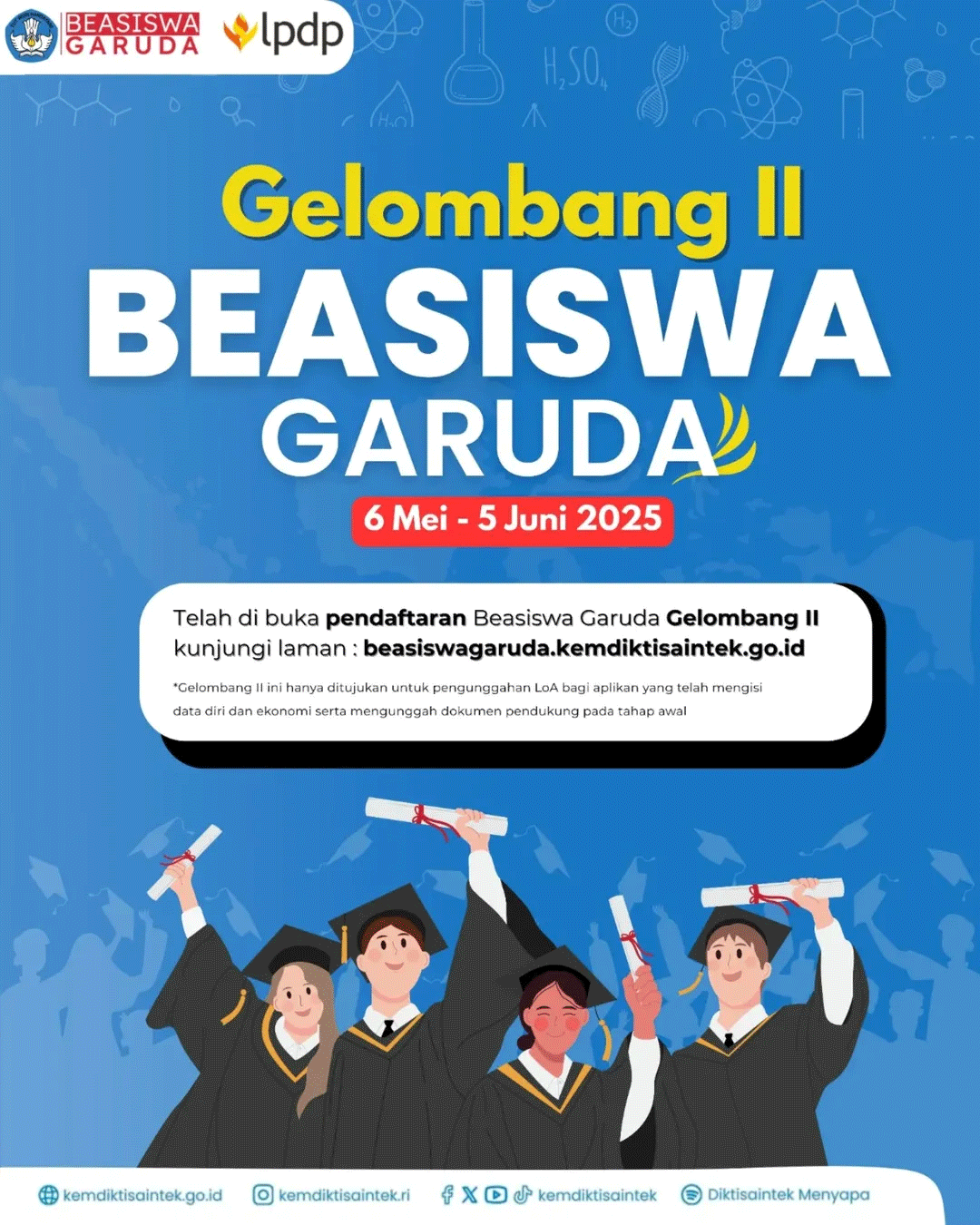
SCROLL TO RESUME CONTENT
Budaya self-diagnose sebenarnya tidak sepenuhnya negatif. Di satu sisi, ia mendorong kesadaran publik terhadap pentingnya kesehatan mental. Banyak orang yang dulunya menyepelekan stres kini mulai terbuka membicarakan emosi dan kesejahteraan psikologis. Bahkan, beberapa influencer psikologi membantu audiensnya memahami konsep dasar kesehatan mental dengan bahasa sederhana.
Namun, di sisi lain, self-diagnose bisa menjadi bumerang berbahaya. Ketika seseorang salah memahami gejalanya, mereka bisa mengambil langkah keliru seperti menolak terapi profesional, mengonsumsi obat tanpa resep, atau menormalisasi gangguan serius dengan dalih “aku memang seperti ini”.
Mispersepsi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang memperkuat konten serupa. Semakin sering seseorang menonton video bertema kesehatan mental, semakin banyak konten serupa yang ditampilkan. Akhirnya, terbentuk echo chamber psikologis di mana pengguna hanya melihat narasi yang mendukung “diagnosa diri” mereka.
Pentingnya Literasi Digital dan Kesehatan Mental
Kunci menghadapi fenomena ini adalah literasi digital dan edukasi psikologi dasar. Pengguna perlu memahami bahwa tidak semua informasi di media sosial valid secara ilmiah. Diagnosis kesehatan mental hanya bisa ditegakkan oleh psikolog atau psikiater melalui proses asesmen yang terstandar.
Media sosial seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran, bukan menggantikan peran tenaga profesional. Mengonsumsi konten psikologi boleh, tapi tetap perlu disaring dengan berpikir kritis.
Sebagai pengguna aktif dunia digital, sudah saatnya masyarakat belajar membedakan antara edukasi dan sugesti, antara empati dan simplifikasi. Self-diagnose bisa menjadi titik awal untuk mengenal diri, tetapi bukan akhir dari proses penyembuhan.(*)
*Reporter: Angnis Arimayanti